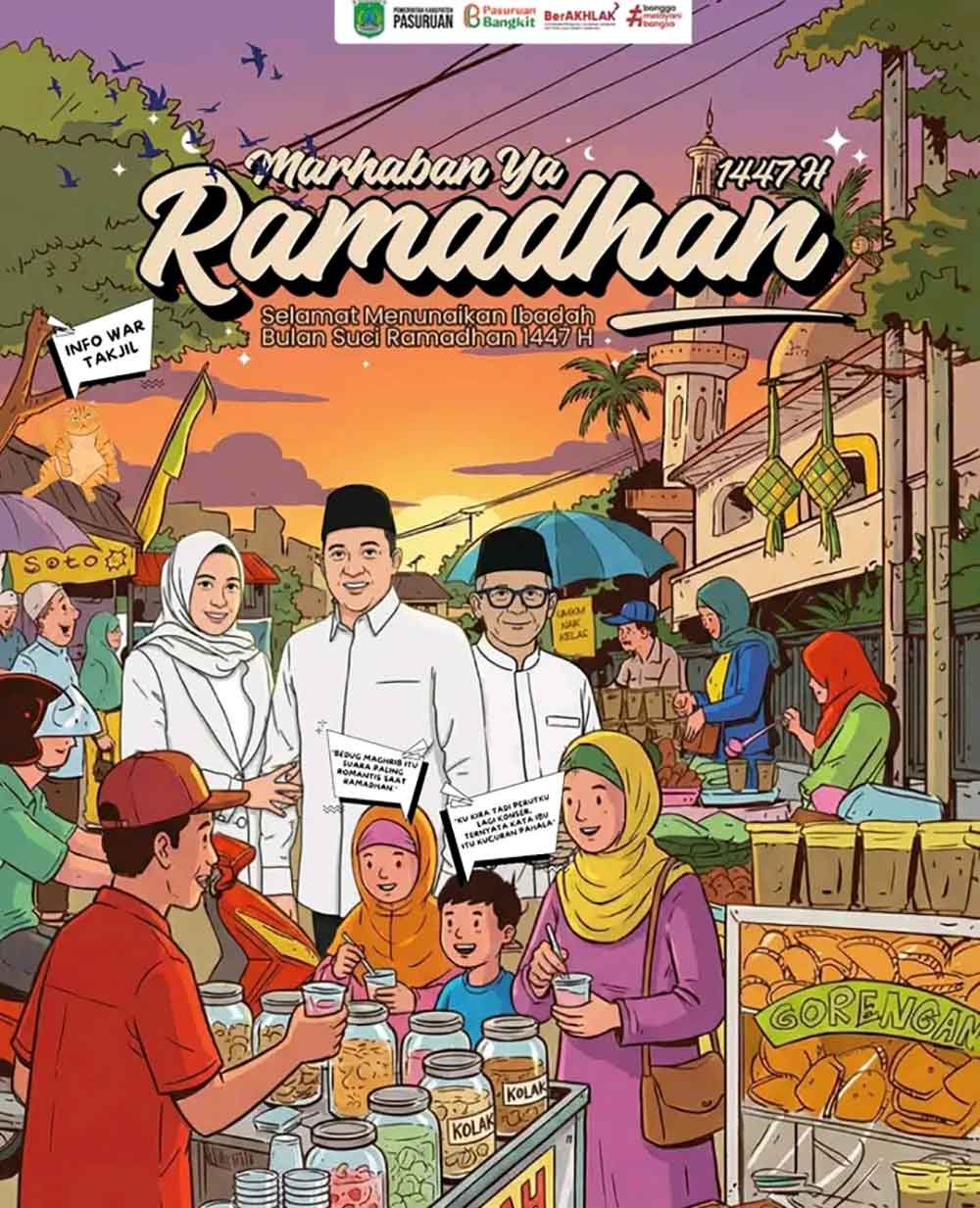Mantan Sekjen DPP GMNI, Muh. Ageng Dendy Setiawan.
Mantan Sekjen DPP GMNI, Muh. Ageng Dendy Setiawan.
Oleh: Muh. Ageng Dendy Setiawan
Pilkada atau Pemilihan kepala daerah selalu menjadi jantung perdebatan demokrasi di Indonesia. Ia bukan hanya membahas secara teknis memilih gubernur, bupati, atau wali kota, melainkan menyangkut cara negara memaknai kedaulatan rakyat, efisiensi pemerintahan, serta tujuan akhir dari demokrasi itu sendiri, yakni kesejahteraan rakyat.
Di tengah dominasi narasi pilkada langsung, mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD kerap diposisikan sebagai sesuatu yang usang, elitis, bahkan anti-demokrasi. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, mekanisme ini memiliki dasar konseptual, historis, dan argumentasi kebijakan yang tidak sesederhana stigma yang dilekatkan kepadanya.
Secara konseptual, pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah sistem di mana rakyat tidak memilih kepala daerah secara langsung, melainkan terlebih dahulu memilih wakil-wakilnya di DPRD melalui pemilu legislatif.
DPRD kemudian menjalankan mandat perwakilan itu dengan memilih kepala daerah dalam rapat paripurna. Kepala daerah terpilih bertanggung jawab secara politik kepada DPRD, bukan langsung kepada rakyat.
Dalam konstruksi ini, DPRD berfungsi sebagai electoral college—lembaga pemilih—bukan sekadar lembaga pengawas. Kedaulatan rakyat tidak dihapus, tetapi disalurkan melalui mekanisme perwakilan institusional.
Model seperti ini bukanlah hal asing dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pada masa awal Reformasi, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kepala daerah dipilih oleh DPRD sebagai bagian dari agenda desentralisasi dan penguatan parlemen lokal pasca-Orde Baru.
Secara konstitusional, mekanisme ini tidak bertentangan dengan UUD 1945. Bahkan, pemerintah secara resmi menegaskan bahwa konstitusi tidak melarang kepala daerah dipilih oleh DPRD, selama prosesnya demokratis, transparan, dan akuntabel. Artinya, wacana pilkada DPRD memiliki basis historis dan konstitusional yang sah untuk dikaji ulang.
Namun pengalaman periode 1999–2004 juga meninggalkan pelajaran penting. Politik uang, transaksi elit, dan kepala daerah yang tersandera kepentingan fraksi menjadi fenomena nyata. Kritik inilah yang kemudian melahirkan pilkada langsung sejak 2005.
Sejak saat itu, demokrasi seolah direduksi menjadi kehadiran rakyat di bilik suara. Partisipasi langsung diposisikan sebagai satu-satunya ukuran keabsahan demokrasi, sementara dimensi hasil dan dampak kebijakan kerap terpinggirkan.
Dua dekade kemudian, pilkada langsung justru memperlihatkan problem struktural baru, terutama tingginya biaya politik. Berbagai kajian akademik dan laporan pemantauan pemilu menunjukkan bahwa biaya pencalonan kepala daerah di Indonesia telah mencapai tingkat yang tidak rasional.
Untuk level bupati dan wali kota, biaya politik kandidat dapat mencapai puluhan miliar rupiah, bahkan dalam banyak kasus menyentuh angka Rp30 miliar. Pada level gubernur, kebutuhan dana politik bisa melonjak hingga Rp100 miliar atau lebih—angka yang jauh melampaui total penghasilan resmi seorang kepala daerah selama masa jabatan.
Beban biaya politik yang besar ini memaksa kandidat mencari dukungan sponsor, pengusaha, atau jejaring modal politik. Secara struktural, kondisi tersebut memperbesar peluang praktik politik uang, relasi patron-klien, dan korupsi kebijakan.
Sejumlah riset antikorupsi mencatat bahwa kepala daerah terpilih kerap melakukan praktik “balik modal” melalui jual beli jabatan, suap perizinan, dan penyalahgunaan anggaran publik. Dalam konteks ini, masalah pilkada langsung bukan sekadar persoalan moral individu, melainkan adanya dugaan problem sistemik dari demokrasi elektoral yang mahal.
Pemilihan kepala daerah melalui DPRD menawarkan alternatif untuk menekan biaya politik tersebut. Dengan memindahkan arena kompetisi dari ruang elektoral massal ke ruang institusional, ketergantungan pada modal finansial dapat dikurangi.
Proses seleksi lebih memungkinkan fokus pada rekam jejak, kapasitas teknokratis, dan visi kebijakan jangka menengah-panjang, alih-alih sekadar popularitas dan kekuatan kampanye.
Dari sisi anggaran publik, pilkada langsung juga menimbulkan beban fiskal yang signifikan. Penyelenggaraan pilkada serentak 2024, misalnya, dilaporkan menelan anggaran negara hingga sekitar Rp41 triliun, meskipun jadwal pemilihan telah diserentakkan untuk menekan biaya.
Angka ini belum mencakup biaya kampanye kandidat, logistik tambahan, serta pengamanan yang dalam praktiknya kerap dibebankan pada APBD. Bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, pilkada langsung menjadi beban struktural yang menggerus ruang belanja publik.
Dalam perspektif asas manfaat, efisiensi penggunaan sumber daya publik menjadi ukuran penting kualitas demokrasi. Anggaran yang terserap untuk kontestasi elektoral mahal berpotensi mengorbankan kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan.
Pemilihan melalui DPRD, dengan biaya penyelenggaraan yang jauh lebih rendah, membuka ruang pengalihan anggaran ke sektor-sektor produktif yang manfaatnya langsung dirasakan rakyat.
Manfaat lain yang kerap luput dari perdebatan adalah dimensi sosial. Pilkada langsung dalam praktiknya sering memicu polarisasi tajam, politik identitas, dan konflik horizontal, terutama di daerah dengan kerentanan sosial.
Pemilihan oleh DPRD mengalihkan kontestasi dari ruang sosial ke ruang institusional, sehingga mengurangi gesekan di tingkat akar rumput. Bagi daerah rawan konflik, stabilitas sosial semacam ini merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan.
Selain itu, mekanisme DPRD berpotensi menekan populisme dan politik pencitraan. Pilkada langsung mendorong kampanye emosional, janji instan tanpa basis kebijakan, serta politik viral yang simbolik.
Dalam pemilihan oleh DPRD, seleksi dapat diarahkan pada kelayakan substantif, yakni kapasitas kepemimpinan, integritas, dan visi pembangunan. Asas manfaat diwujudkan melalui kepemimpinan yang rasional dan programatik, bukan sekadar populer secara elektoral.
Dari perspektif kelembagaan, pilkada melalui DPRD juga berpotensi memperbaiki kualitas partai politik. Partai didorong menjalankan kaderisasi serius karena calon kepala daerah lahir dari proses institusional, bukan figur instan atau selebritas politik. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi pada pelembagaan demokrasi perwakilan dan menekan dominasi oligarki personal.
Secara teoritis, mekanisme ini sejalan dengan Teori Demokrasi Perwakilan Edmund Burke. Burke menolak pandangan wakil rakyat sebagai delegate yang sekadar mengikuti kehendak mayoritas sesaat.
Bagi Burke, wakil rakyat adalah trustee—pemegang amanah—yang dipilih karena kebijaksanaan dan kapasitasnya, serta berkewajiban menggunakan penilaian moral dan intelektualnya demi kepentingan umum. Dalam konteks pilkada oleh DPRD, anggota DPRD diandaikan bertindak sebagai trustee dalam memilih kepala daerah terbaik bagi daerahnya.
Argumen ini diperkuat oleh Teori Efisiensi Institusional dalam kerangka New Institutionalism, yang menekankan bahwa kualitas demokrasi ditentukan oleh kemampuan institusi menghasilkan keputusan publik secara efektif, dengan biaya politik dan sosial yang minimal, serta output kebijakan yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Demokrasi yang prosedurnya mahal, penuh konflik, dan tidak efektif justru berpotensi merugikan publik.
Salah satu tuduhan paling sering diarahkan pada mekanisme pilkada melalui DPRD adalah risiko elite capture—yakni pembajakan keputusan politik oleh segelintir elite partai dan kepentingan oligarkis. Kritik ini terdengar meyakinkan, tetapi problematis jika tidak disertai refleksi jujur terhadap realitas pilkada langsung.
Fakta menunjukkan bahwa elite capture tidak hilang dalam pilkada langsung; ia hanya berpindah bentuk. Dominasi pemodal besar, sponsor politik, dan dinasti kekuasaan justru menemukan ruang lebih luas dalam kontestasi elektoral yang mahal. Dengan kata lain, pemilihan langsung tidak menghapus elite capture, melainkan sering kali memfasilitasinya secara lebih masif dan mahal.
Dalam mekanisme DPRD, setidaknya elite capture dapat ditarik ke ruang institusional yang relatif lebih mudah diawasi melalui transparansi sidang, keterbukaan rekam jejak voting, pengawasan publik, dan sanksi etik.
Masalah utamanya bukan terletak pada sistem perwakilannya, melainkan pada lemahnya regulasi dan pengawasan. Karena itu, menjadikan elite capture sebagai alasan absolut untuk menolak pilkada DPRD justru menutup mata terhadap fakta bahwa sistem langsung pun tidak imun dari pembajakan elite.
Tentu saja, pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak boleh mengulang kegagalan masa lalu. Transparansi proses, akuntabilitas politik, pengawasan publik yang kuat, dan sanksi tegas terhadap praktik transaksional menjadi prasyarat mutlak. Namun menutup ruang diskusi atas alternatif ini sama saja dengan membekukan demokrasi itu sendiri.
Pada akhirnya, demokrasi bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sarana untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Dalam kerangka itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD layak dipahami bukan sebagai kemunduran demokrasi, melainkan sebagai opsi kebijakan yang rasional dan konstitusional.
Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang berani mengevaluasi dirinya sendiri, tidak terjebak pada fetisisme prosedur, dan selalu bertanya: untuk siapa kekuasaan dijalankan.
Penulis merupakan mantan Sekjen DPP GMNI