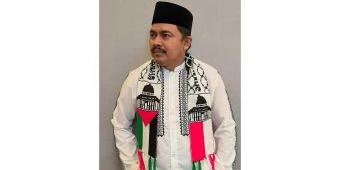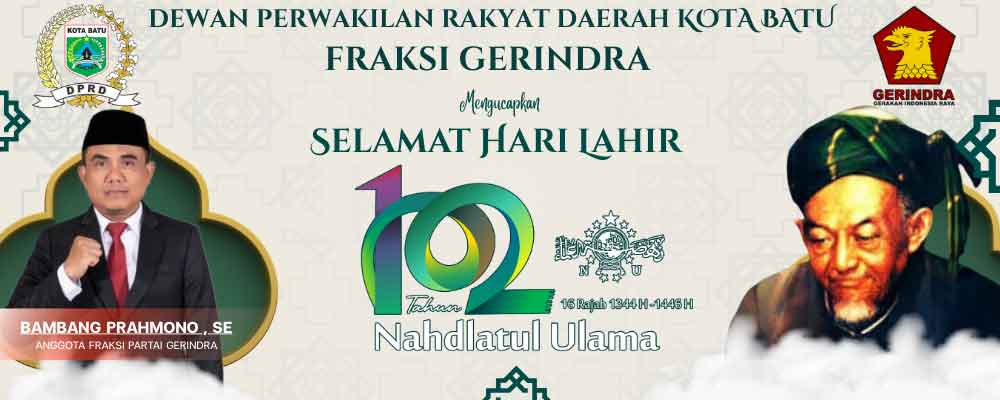Foto ilustrasi Menteri Haji dan Umrah bersama Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA, meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: bangsaonline
Foto ilustrasi Menteri Haji dan Umrah bersama Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA, meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: bangsaonline
Oleh: Ghozi Zainuddin, S.Ag
Ketika pemerintah mencanangkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar dan santri, muncul beragam pandangan dari Masyarakat. Sebagian menyambut dengan antusias, sebagian lain meragukan kesiapan lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Namun jika kita menengok sejarah panjang pesantren di Indonesia, keraguan itu sebetulnya terjawab: pesantren selalu siap — karena tradisi memberi dan berbagi telah menjadi nadi kehidupannya jauh sebelum program ini hadir.
Dalam khazanah pesantren, memberi makan bukan sekadar bantuan sosial, tetapi bagian dari ibadah sosial yang berakar dalam ajaran Rasulullah SAW: “Tidak beriman seseorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.”
Tradisi “berbagi nasi, berbagi berkah” telah lama hidup di setiap pondok, dari dapur sederhana hingga lumbung-lumbung santri yang dibuka untuk mereka yang kekurangan. Maka, MBG bagi pesantren bukan hal baru, melainkan tradisi lama yang kini diformalkan oleh negara.
Kesiapan Pesantren: Tradisi yang Telah Terinstitusi
Pesantren tidak perlu menunggu program pemerintah untuk belajar memberi. Setiap hari, pengasuh pesantren dan para ustaz telah menanamkan semangat infāq dan shadaqah dalam bentuk paling nyata: menyediakan makan bagi santri. Bagi para kiai, memberi makan santri bukan sekadar tanggung jawab logistik, melainkan bagian dari keberkahan ilmu.
Dalam banyak pesantren, dapur telah menjadi pusat spiritual: tempat di mana kesederhanaan diolah menjadi keberkahan. Tidak ada santri yang dibiarkan lapar, karena prinsip pesantren bukan efisiensi, melainkan kasih sayang yang menumbuhkan kemandirian. Maka, ketika MBG datang dengan format kebijakan, pesantren hanya perlu menyelaraskan tata kelolanya dengan mekanisme formal bukan membangun dari nol.
Inilah yang membedakan pesantren dari lembaga pendidikan lain: sistem sosialnya telah terbentuk dari habitus (gaya hidup) berbagi. Ia tidak hanya siap secara fisik, tetapi siap secara mental dan moral. Program MBG hanya menambah bentuk baru dari tradisi lama yang telah hidup: “makan bersama dengan barokah.”
Kekuatan Sumber Daya Manusia Pesantren
Kesiapan pesantren tidak hanya terletak pada nilai-nilai, tetapi juga pada sumber daya manusianya (SDM). Pesantren adalah komunitas hidup yang berisi beragam peran: santri, ustaz, pengasuh, dapur umum, hingga alumni yang terlibat aktif. Jaringan sosial ini telah bekerja seperti sistem yang saling melengkapi, bahkan tanpa struktur birokrasi yang rumit.
Banyak pesantren memiliki tim logistik, bagian perlengkapan, dan dapur umum yang dikelola secara gotong royong. Mereka terbiasa mengelola konsumsi ratusan bahkan ribuan santri setiap hari, dengan sistem yang efisien dan hemat. Jika MBG mensyaratkan tata kelola pangan dan gizi, pesantren hanya perlu memperkuat aspek administratifnya, bukan membangun struktur baru.
Selain itu, pesantren tidak kekurangan orang-orang yang kompeten. Banyak di antara alumni dan pengurus yang memiliki keahlian dalam bidang gizi, kesehatan, manajemen, dan agribisnis. Jika negara membuka ruang kolaborasi, maka pesantren justru dapat menjadi mitra strategis — bukan hanya penerima manfaat, tetapi pengelola yang andal.
Pemahaman terhadap Santri dan Pemetaan Kebutuhan
Keunggulan pesantren yang jarang disadari adalah kemampuannya membaca kebutuhan santri secara tepat. Tidak semua santri datang dari latar belakang ekonomi yang sama; sebagian berasal dari keluarga mampu, sebagian lain datang dari pelosok dengan bekal yang terbatas.
Namun pesantren memiliki sistem sosial yang alami dan halus dalam memetakan siapa yang membutuhkan bantuan lebih. Tidak ada diskriminasi, tidak ada label “santri miskin.” Yang ada hanyalah kebersamaan dalam keberkahan. Santri yang berkecukupan sering membantu yang kekurangan, dan semuanya makan di meja yang sama.
Dengan kemampuan ini, pesantren dapat menjalankan MBG secara adil dan efisien. Pengasuh dan para ustaz mengenal santrinya secara personal; mereka tahu siapa yang harus didahulukan tanpa perlu survei panjang. Sistem sosial berbasis kedekatan inilah yang menjadikan pesantren sangat adaptif terhadap program semacam ini.
Menjawab Sorotan: Pesantren dan Keterbukaan Sosial
Belakangan ini, pesantren kerap menjadi sorotan publik — sebagian karena isu regulasi, sebagian karena kasus yang terjadi di luar kendali lembaga. Dalam konteks itulah, tulisan ini ingin memberikan masukan yang konstruktif: bahwa cara terbaik untuk menguatkan pesantren bukan dengan kecurigaan, tetapi dengan kepercayaan dan pendampingan.
Pesantren adalah lembaga moral yang tumbuh dari kepercayaan masyarakat. Ia tidak berdiri karena modal, tetapi karena barokah. Maka, setiap kebijakan yang menyentuh pesantren perlu diletakkan dalam kerangka penghormatan terhadap nilai-nilainya. Program MBG, misalnya, harus dilihat bukan sekadar program unggulan pemerintah dan proyek pangan, tetapi sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang membentuk karakter dan kebersamaan.
Negara tidak perlu “mengajari” pesantren tentang berbagi; yang perlu dilakukan adalah membantu memperkuat kapasitasnya agar tradisi itu dapat dikelola lebih baik, transparan, dan berkelanjutan.
Dampak Ekonomi dan Sosial bagi Masyarakat Sekitar
Program MBG di pesantren tidak hanya berpengaruh pada kualitas gizi santri, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat sekitar. Dalam satu siklus penyediaan makan harian, pesantren akan membutuhkan bahan pangan seperti beras, sayur, buah, telur, daging, hingga bumbu dapur. Jika seluruh kebutuhan itu diserap dari petani, peternak, dan pedagang lokal, maka efek ganda (multiplier effect) akan sangat besar.
Pekerja harian, pedagang pasar, dan pelaku usaha kecil di sekitar pesantren akan mendapatkan manfaat langsung. Pesantren akan menjadi pusat ekonomi rakyat — micro-ecosystem yang menghidupi lingkungannya. Dengan demikian, MBG bukan sekadar program makan gratis, tetapi juga strategi pemberdayaan lokal yang berakar pada prinsip taʿāwun (tolong menolong).
Harapannya, kebijakan ini dijalankan dengan mekanisme partisipatif: melibatkan pengasuh pesantren dalam perencanaan, memperkuat kapasitas dapur dan SDM lokal, serta membuka peluang kemitraan dengan pelaku bisnis mikro di sekitar pondok. Dengan demikian, keberkahan MBG tidak berhenti di meja makan santri, tetapi mengalir ke seluruh lapisan masyarakat.
Dari Tradisi ke Kebijakan
Pesantren telah hidup selama berabad-abad dengan nilai berbagi dan kepedulian sosial yang mendalam. Program MBG hanyalah bentuk formal dari tradisi yang sudah berakar: tradisi memberi makan dengan cinta, memberi berkah dengan doa, dan memberi manfaat dengan keikhlasan.
Kesiapan pesantren bukan karena mereka modern, tetapi karena mereka beradab. Adab memberi, adab memuliakan sesama, dan adab memandang rezeki sebagai amanah.
Oleh karena itu, bila negara ingin membangun bangsa yang sehat jasmani dan rohani, maka pesantren harus ditempatkan bukan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai mitra peradaban.
Sebab di sanalah hidup nilai yang kini mulai hilang di dunia modern: nilai ikhlas memberi tanpa menunggu kembali.
Dan mungkin, justru dari dapur-dapur sederhana pesantrenlah, Indonesia akan menemukan kembali arti pembangunan yang berjiwa di zaman modern.
Penulis, Ketua JASMINU Indonesia Maju