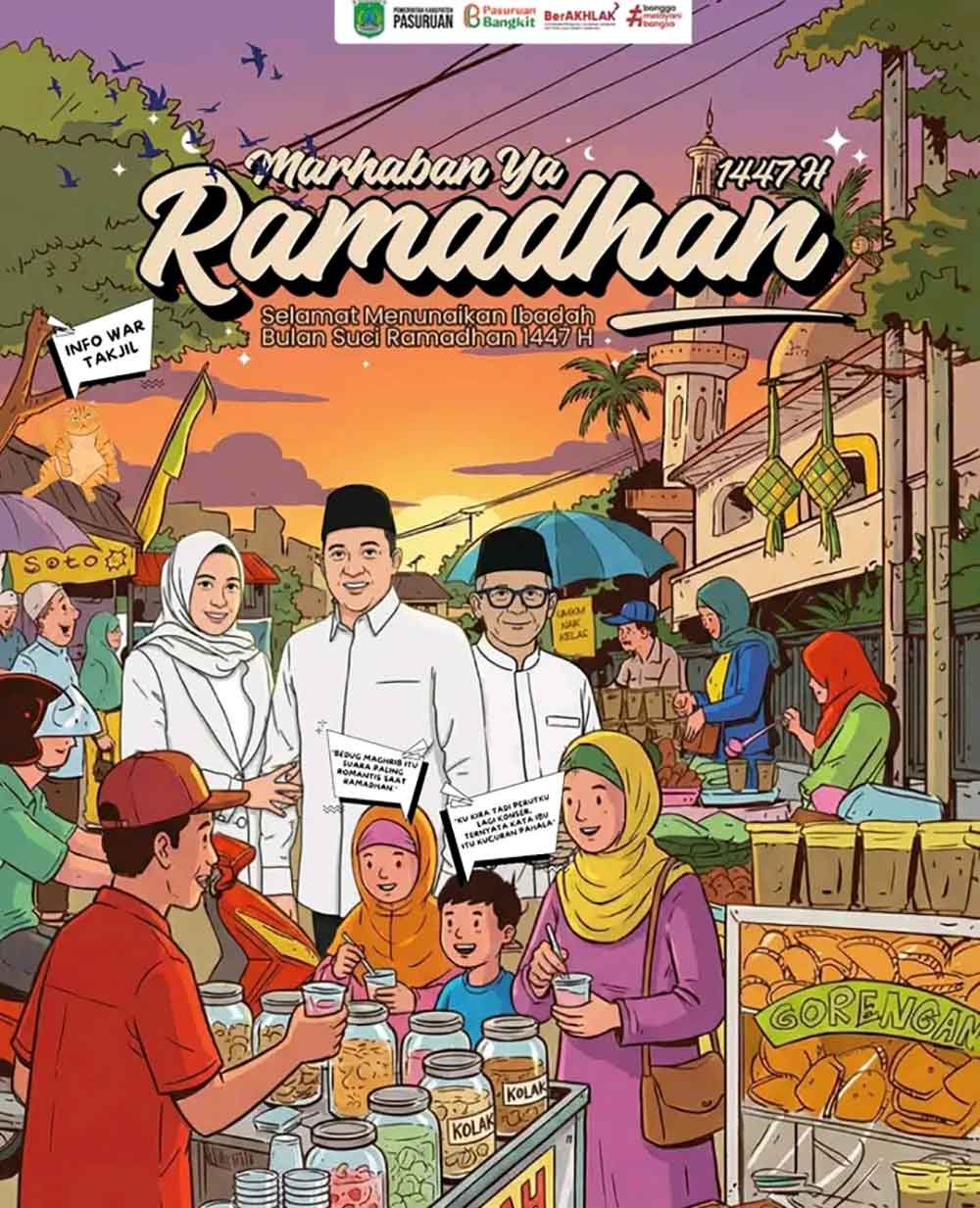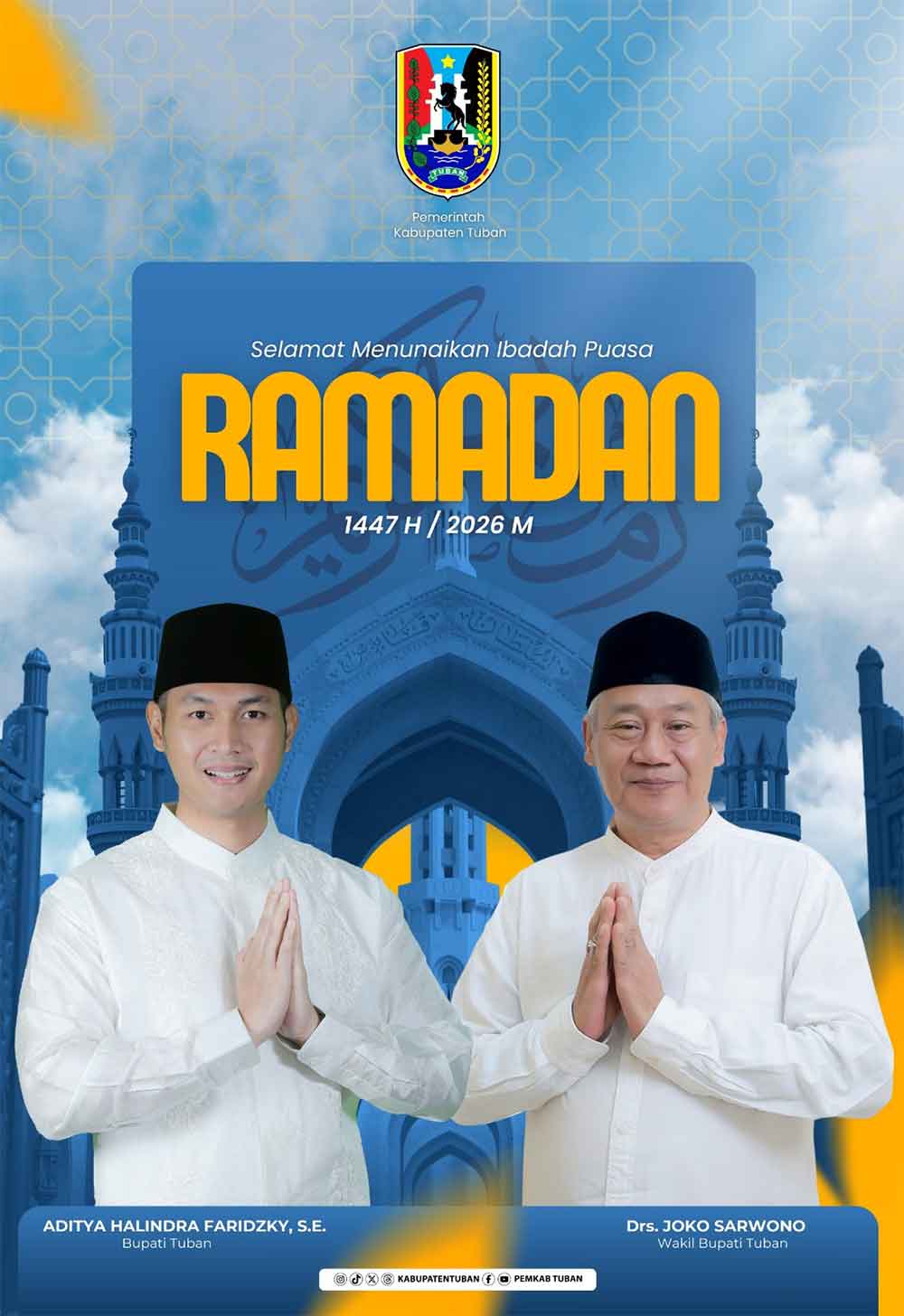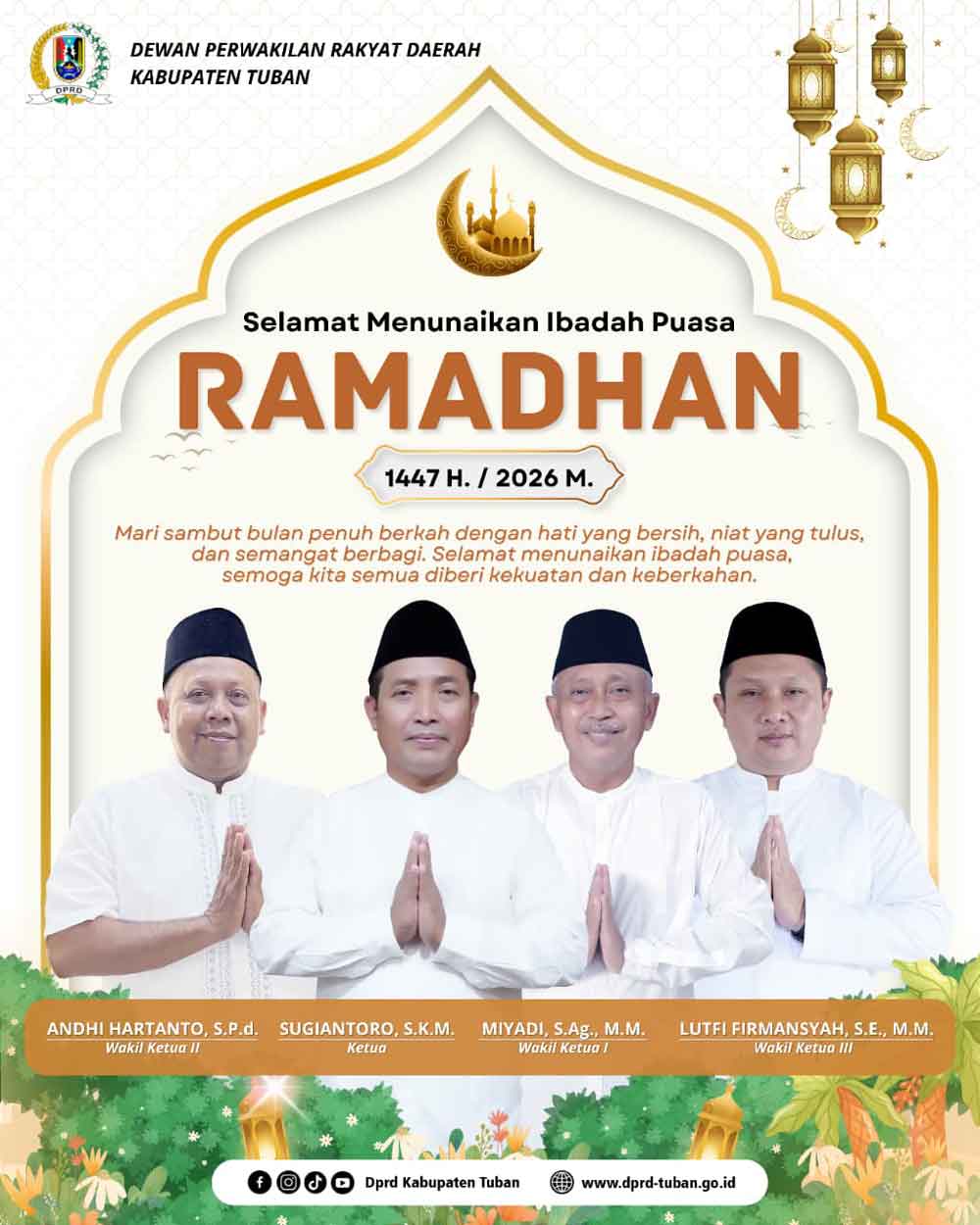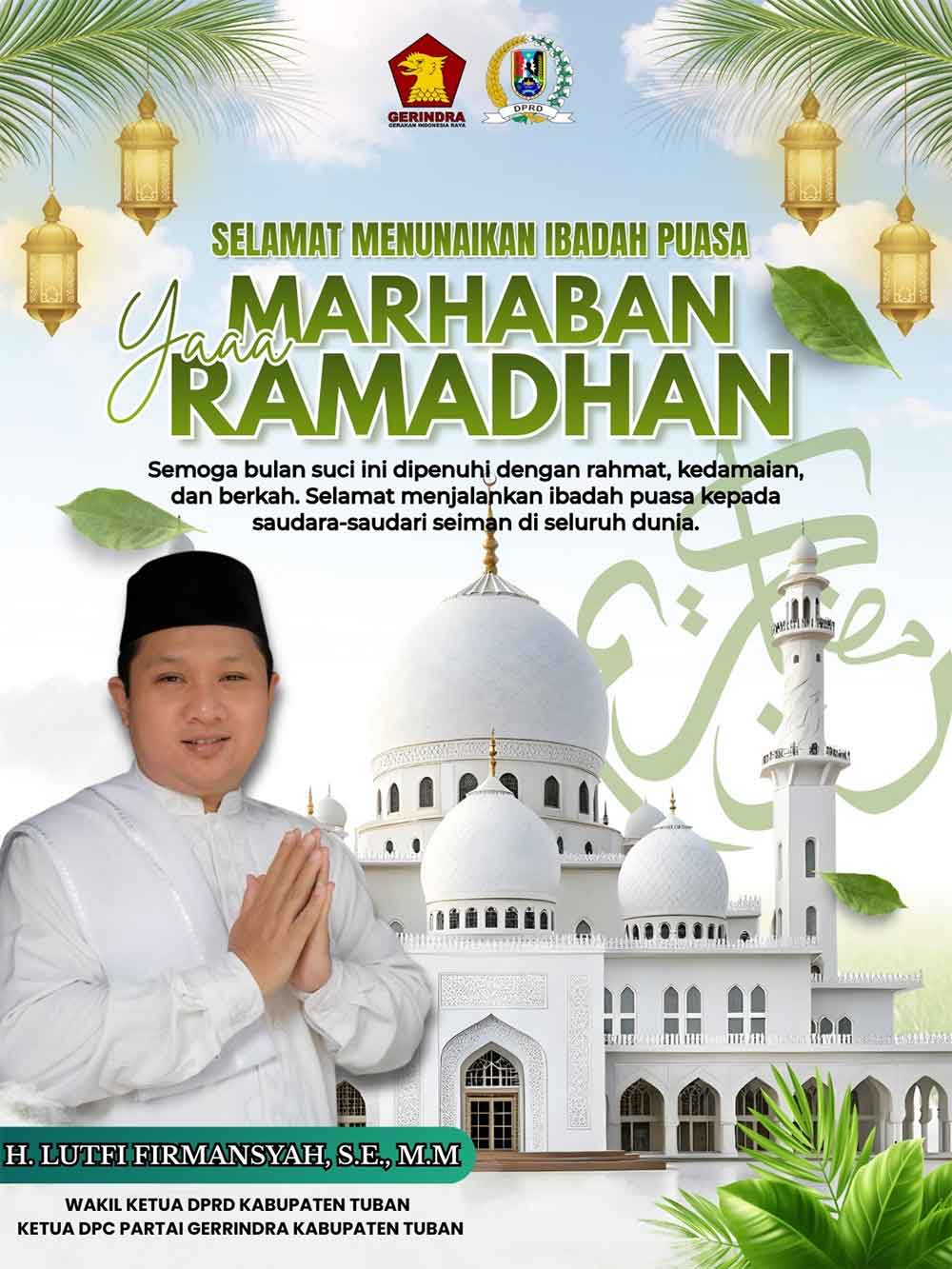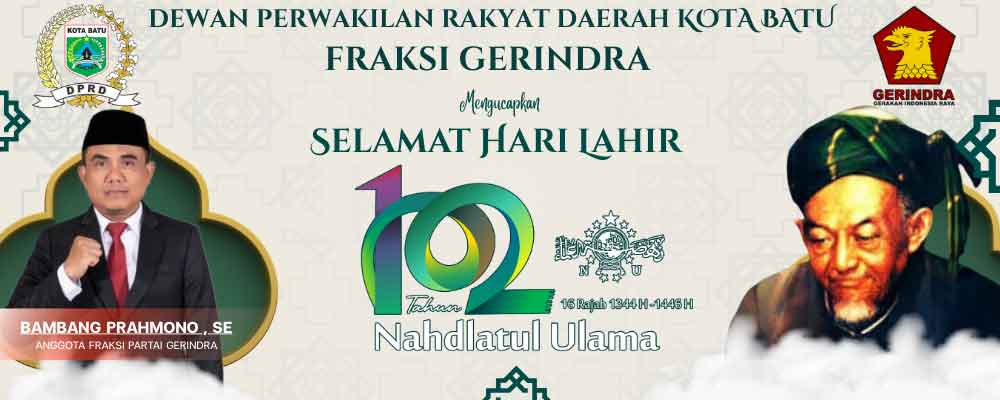Khariri Makmun. Foto: dok. pribadi
Khariri Makmun. Foto: dok. pribadi
Oleh : Khariri Makmun*
Di dunia geopolitik, perang teritorial tidak selalu dimulai dengan kontak senjata atau peluncuran rudal. Kadang, perang dimulai dari sesuatu yang terlihat sepele: perubahan nama. Itulah yang kini terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Malaysia, lewat Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan, baru-baru ini secara resmi menyebut wilayah maritim yang selama ini kita kenal sebagai Blok Ambalat dengan nama lain—Laut Sulawesi. Alasan mereka sederhana sekaligus sarat makna: istilah “Ambalat” dianggap sebagai narasi Indonesia yang mempertegas klaim kedaulatan, sementara Malaysia ingin membingkai ulang kawasan itu sesuai peta 1979 dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 terkait Pulau Sipadan dan Ligitan.
Bagi publik awam, mungkin ini sekadar pergantian istilah. Namun dalam diplomasi, nama adalah senjata. Ia menjadi pijakan psikologis, mengubah persepsi internasional, dan pelan-pelan membangun normalisasi terhadap sebuah klaim. Ketika Malaysia menolak istilah “Ambalat” dan memaksakan “Laut Sulawesi”, mereka tidak sekadar berdebat soal nomenklatur, melainkan sedang membangun kerangka legitimasi politik dan hukum bahwa blok ND-6 dan ND-7 adalah bagian dari yurisdiksi mereka. Ini adalah bentuk “soft claim”—mengokohkan posisi tanpa harus mengirim kapal perang.
Konteksnya tidak berdiri sendiri. Sengketa Ambalat telah berlangsung sejak 2005, bermula dari tumpang tindih klaim batas maritim setelah ICJ memenangkan Malaysia dalam kasus Sipadan-Ligitan. Putusan itu sebenarnya hanya mengatur soal dua pulau tersebut, tidak menyentuh delimitasi batas laut di sekitarnya. Tetapi Malaysia memanfaatkannya untuk memperluas proyeksi Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan peta 1979 yang sejak awal ditolak Indonesia. Di atas kertas, peta itu adalah deklarasi sepihak. Namun di meja diplomasi, ia kerap dijadikan referensi pembicaraan, apalagi bila Indonesia lengah dalam membangun kontra-narasi.
Yang membuat Ambalat begitu seksi bagi dua negara bukan hanya lokasinya yang strategis di Laut Sulawesi, tetapi juga isi perutnya. Survei geologi memperkirakan ada cadangan 764 juta barel minyak dan gas di wilayah ini, cukup untuk menopang konsumsi energi selama puluhan tahun. Nilai ekonominya triliunan rupiah, nilai strategisnya tak ternilai. Tak heran, sejak dua dekade lalu kapal-kapal patroli kedua negara kerap beradu pandang di sini, bahkan beberapa kali nyaris beradu fisik.
Langkah Malaysia mengganti istilah menjadi “Laut Sulawesi” patut dibaca sebagai strategi dua lapis. Lapisan pertama, mengubah persepsi domestik mereka sendiri. Dengan nama ini, isu Ambalat dihadirkan sebagai bagian dari yurisdiksi Malaysia di Sabah, menghindari narasi “sengketa” yang bisa memicu protes internal. Lapisan kedua, menguji reaksi Indonesia—apakah kita akan membiarkannya mengendap sebagai fakta baru, atau mengajukan protes diplomatik yang tegas. Karena dalam hukum internasional, pengakuan diam-diam (tacit recognition) bisa menjadi amunisi kuat bagi pihak yang bersengketa.
Di Jakarta, DPR bereaksi keras. Mereka melihat klaim ini bukan sekadar sengketa teknis, melainkan potensi ancaman terhadap keutuhan wilayah dan persepsi publik tentang kedaulatan negara. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri diminta segera memberikan klarifikasi resmi dan mengambil langkah tegas. Dubes RI untuk Malaysia, Hermono, dilaporkan telah menyampaikan laporan ke Menlu Retno Marsudi. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan pernyataan, menekankan harapan agar sengketa ini diselesaikan secara konstruktif. Namun, kata-kata harus diikuti langkah nyata.
Dalam diplomasi maritim, perang yang paling menentukan bukanlah di garis batas laut, melainkan di meja negosiasi dan ruang pemberitaan internasional. Malaysia sudah memulai langkah framing. Jika Indonesia tidak segera mengimbangi, narasi mereka bisa lebih cepat diterima di forum internasional, sementara istilah “Ambalat” perlahan menghilang dari peta dunia. Di era media global, siapa yang lebih konsisten mengulang sebuah istilah, dialah yang membentuk persepsi.
Opsi yang tersedia bagi Indonesia ada dua: konfrontasi diplomatik atau negosiasi kreatif. Konfrontasi diplomatik berarti mengajukan protes resmi di forum bilateral dan multilateral, mempertegas posisi hukum kita berdasarkan UNCLOS dan sejarah eksplorasi migas di kawasan tersebut. Negosiasi kreatif berarti mempertimbangkan skema pengelolaan bersama (joint development), sebagaimana yang pernah dilakukan beberapa negara di wilayah sengketa Laut Cina Selatan. Skema ini bisa menjadi jalan tengah untuk menghindari konflik terbuka, sambil tetap menjaga klaim kedaulatan.
Namun, joint development bukan tanpa risiko. Ia bisa dibaca sebagai kompromi politik yang melemahkan posisi klaim Indonesia di masa depan. Jika tidak diatur dengan ketat—misalnya dengan klausul “without prejudice” yang memastikan tidak ada pengakuan kedaulatan tersirat—skema ini justru akan merugikan kita. Malaysia tentu memahami hal ini, dan akan berusaha memanfaatkan setiap celah.
Karena itu, strategi Indonesia harus berjalan di dua jalur. Jalur pertama adalah mempertahankan narasi “Ambalat” di semua kanal, mulai dari pernyataan resmi pemerintah, dokumen hukum, peta nasional, hingga pemberitaan media. Jalur kedua adalah membangun koalisi diplomatik di ASEAN dan PBB untuk menegaskan bahwa status kawasan ini masih dalam sengketa, sehingga setiap upaya penamaan sepihak tidak memiliki kekuatan hukum. Kemenangan di ranah opini publik internasional seringkali menjadi modal kuat untuk meraih hasil di meja perundingan.
Pengalaman di berbagai sengketa maritim dunia menunjukkan bahwa perebutan nama dan istilah sering menjadi langkah awal untuk mengamankan klaim. Jepang menyebut “Laut Jepang” meski Korea Selatan menyebutnya “Laut Timur”. Cina menyebut “Laut Cina Selatan” meski Vietnam punya istilah sendiri. Begitu istilah itu diterima secara luas, ia menjadi bagian dari realitas geopolitik yang sulit dibalikkan. Malaysia tampaknya tengah mencoba resep yang sama.
Kita tidak bisa meremehkan perang simbol ini. Kedaulatan bukan hanya ditentukan oleh garis koordinat di laut, tapi juga oleh kata-kata yang diucapkan, ditulis, dan diulang setiap hari. Dalam konteks Ambalat, mempertahankan nama adalah mempertahankan klaim. Diam adalah menyerah diam-diam. Reaksi emosional memang harus dihindari, tapi respons yang cepat, terukur, dan konsisten jauh lebih penting.
Ambalat adalah cermin dari betapa rapuhnya batas negara jika tidak dijaga dengan kecerdasan geopolitik. Bukan berarti kita harus mengirim kapal perang setiap kali ada klaim sepihak. Tetapi kita harus hadir di setiap meja perundingan, setiap forum internasional, dan setiap halaman media untuk memastikan cerita yang dibaca dunia adalah cerita kita. Malaysia sudah memulai langkahnya. Kini giliran Indonesia untuk memastikan langkah itu tidak menjadi bab pembuka dari kehilangan yang lebih besar.
Mengapa Malaysia Semakin Berani
Pertanyaan paling penting dalam sengketa ini bukanlah “apa” yang dilakukan Malaysia, tapi “mengapa sekarang”. Mereka bisa saja mengganti istilah sejak 2010 atau 2015. Namun mereka menunggu. Dan ketika akhirnya langkah itu diambil, pasti ada perhitungan yang matang.
Pertama, Malaysia sedang berada di fase politik domestik yang sensitif. Pemerintah koalisi mereka masih rapuh, dengan tekanan dari partai-partai Sabah dan Sarawak yang selalu menuntut perhatian lebih pada isu perbatasan. Mengganti istilah menjadi “Laut Sulawesi” adalah cara aman untuk memberi sinyal kepada konstituen Sabah bahwa Kuala Lumpur menjaga wilayahnya, tanpa memicu konfrontasi langsung dengan Indonesia. Mereka memberi “kemenangan simbolik” kepada publiknya sendiri, sambil menguji reaksi kita.
Kedua, ada faktor ekonomi yang mendesak. Harga minyak dunia belakangan ini fluktuatif, tapi tren permintaan energi di Asia Tenggara meningkat. Cadangan migas Ambalat, yang setara 764 juta barel, adalah kartu truf bagi siapa pun yang bisa mengaksesnya. Malaysia tahu, setiap langkah memperkuat posisi klaim akan menaikkan daya tawar mereka dalam negosiasi pengelolaan bersama. Mereka ingin memastikan ketika duduk di meja perundingan, mereka tidak datang sebagai pihak “setengah kalah” yang hanya memohon akses.
Ketiga, ini juga soal membaca kondisi tetangga. Mereka melihat Indonesia sedang sibuk di banyak front: transisi pemerintahan pasca-pemilu, penataan kabinet baru, dan konsentrasi besar pada isu-isu domestik seperti pangan, inflasi, dan IKN. Sengketa Ambalat, meski penting, belum menjadi prioritas headline di Jakarta. Itulah celah yang dimanfaatkan. Dalam strategi geopolitik, memilih waktu ketika lawan sibuk di rumah sendiri adalah seni klasik.
Keempat, Malaysia paham bahwa perang simbol selalu lebih murah daripada perang fisik. Mengubah istilah tidak memerlukan kapal perang, tidak menimbulkan korban, dan sulit diprotes keras tanpa terlihat “reaktif berlebihan”. Tapi efeknya bisa jangka panjang: jika istilah itu terus digunakan di dokumen resmi, di media internasional, di forum-forum maritim, maka dalam 10-15 tahun, status quo bisa bergeser.
Kelima, ada konteks regional. ASEAN sedang berusaha menjaga citra sebagai kawasan yang damai dan stabil. Dalam atmosfer seperti ini, pihak yang bisa memosisikan diri sebagai “lebih moderat” akan lebih disukai. Dengan memulai sengketa lewat bahasa yang “netral” — seolah hanya mengoreksi nomenklatur — Malaysia bisa mengklaim posisi itu. Sementara jika Indonesia bereaksi terlalu keras, mereka akan memainkan kartu “kami hanya menyebut nama resmi, mengapa tetangga marah?”. Itu jebakan framing yang harus kita sadari.
Dan inilah yang jarang dibicarakan di ruang publik kita: Malaysia belajar dari pola yang digunakan Cina di Laut Cina Selatan. Cina tidak langsung mengklaim seluruh wilayah dengan kapal perang; mereka mulai dengan peta sembilan garis putus-putus, lalu membangun narasi “historical rights”, lalu membangun pulau buatan. Langkah awal mereka selalu terlihat “tidak mengancam”, tapi konsisten. Malaysia, tentu saja, tidak punya ambisi sebesar Cina, tapi tekniknya mirip: mulai dari narasi, lalu beranjak ke fakta di lapangan.
Celakanya, kita cenderung reaktif hanya ketika ada kapal asing masuk atau ketika ada insiden di lapangan. Perang simbol seperti ini sering kita anggap enteng. Padahal, dalam hukum internasional, pengulangan simbol dan istilah adalah bagian dari *evidence of claim*. Begitu dunia mengadopsi istilah “Laut Sulawesi” untuk wilayah sengketa itu, beban pembuktian di masa depan akan makin berat bagi Indonesia.
Maka jika kita bertanya “kenapa sekarang?”, jawabannya jelas: karena semua faktor berpihak pada Malaysia. Kondisi politik domestik mereka butuh isu ini, kebutuhan energi mereka mendesak, perhatian Indonesia terpecah, harga minyak memberi insentif, dan konteks regional membuat langkah ini relatif aman dari kecaman besar.
Dan jangan lupa, Malaysia bukan cuma bicara. Mereka sudah membuka peluang “pengelolaan bersama” — sebuah manuver yang terdengar manis, tapi penuh jebakan. Jika kita menerimanya tanpa syarat yang jelas, mereka akan mengantongi legitimasi implisit. Jika kita menolaknya mentah-mentah, mereka akan memosisikan diri sebagai pihak yang mau damai sementara Indonesia yang terlihat keras kepala.
Singkatnya, mereka sedang memainkan catur. Kita belum tentu kalah, tapi mereka sudah unggul langkah. Dan di catur geopolitik, unggul satu langkah saja bisa berarti menguasai papan.
* Penulis adalah Direktur Moderation Corner, Jakarta.