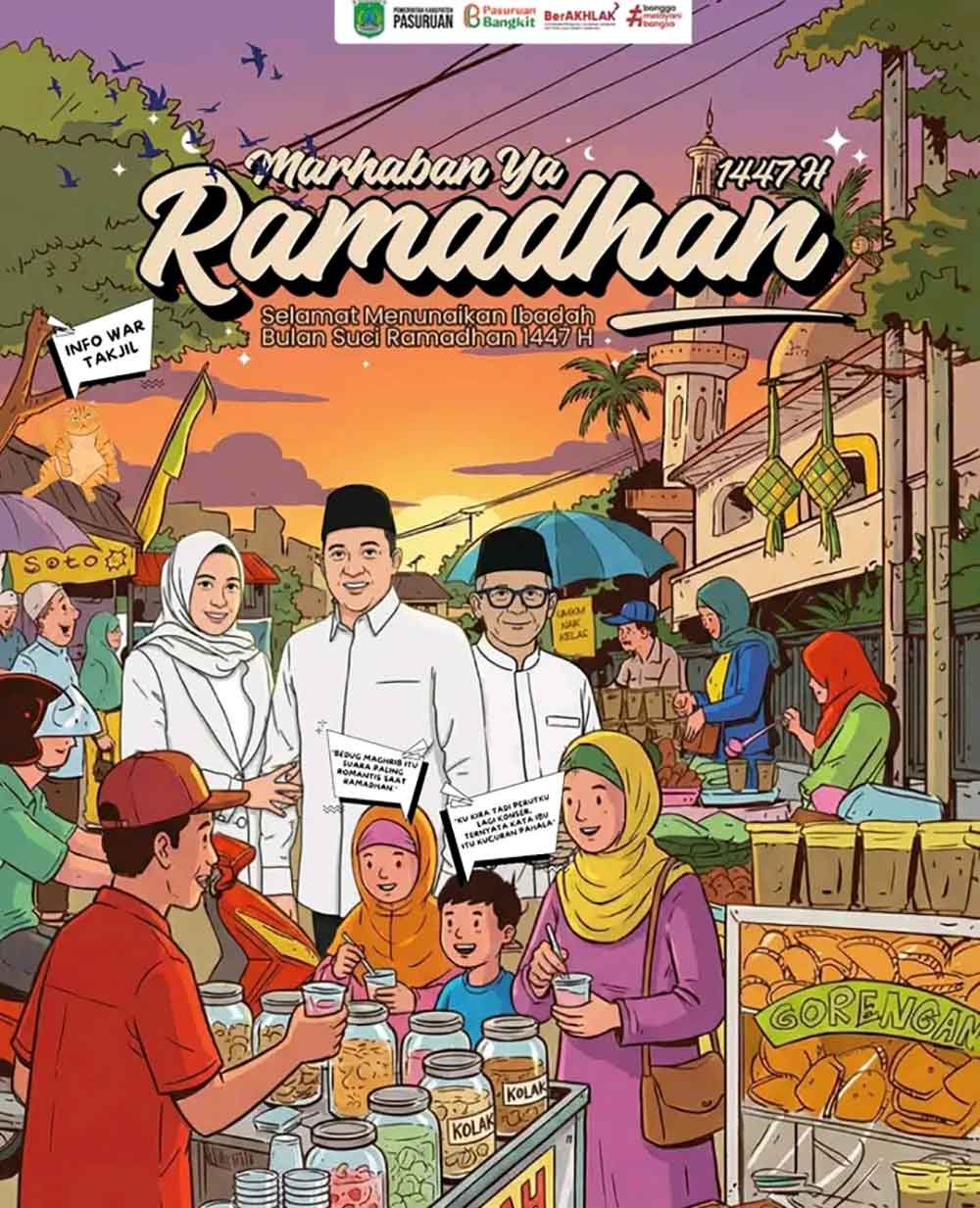Aguk Irawan MN. Foto: dok pribadi
Aguk Irawan MN. Foto: dok pribadi
Oleh: Aguk Irawan MN
Wajah kekuasaan seringkali terbentur pada sesuatu yang banal sekaligus mengerikan: korupsi. Ia bukan sekadar angka yang raib dari kas negara atau perut rakyat yang kian kempis. Di sana, ada yang lebih mendalam sedang runtuh: kehormatan agama.
Sejarah, dalam ingatannya yang paling purba, mencatat bahwa integritas bukanlah sesuatu yang turun begitu saja dari langit tanpa ujian. Bahkan di zaman Nabi SAW, ketika wahyu masih basah di lisan, bayang-bayang ketamakan itu sudah mengintai.
Ibnu Ishaq mencatat peristiwa di Bukit Uhud, ketika segelintir pasukan curiga akan pembagian ghonimah (harta rampasan). Kemudian ada yang ghulul. Sebuah tuduhan yang kemudian dibersihkan oleh langit melalui ayat, namun meninggalkan luka pada gagasan tentang kepercayaan.
Lalu ada Mid’am, atau mungkin Kirkirah. Seorang budak yang gugur di medan perang, yang secara lahiriah tampak sebagai martir. Namun, sebuah mantel yang ia selipkan secara sembunyi-sembunyi—hanya sebuah mantel—membuat Nabi berkata bahwa ia berada di dalam api. Bahkan, Nabipun tidak menyalatinya langsung, sebuah isyarat simbolik bahwa "mantel" yang digelapkan itu kini membakar tubuhnya di alam kubur.
Korupsi, dalam fragmen ini, bukan soal besar kecilnya nominal. Ia adalah soal pengkhianatan terhadap amanah yang membuat "kesalehan visual" menjadi tak berarti. Pun dalam kisah perhiasan seharga dua dirham, atau kasus Abdullah Ibn al-Lutbiyyah, sang pemungut zakat yang mencoba melegalkan gratifikasi dengan dalih "hadiah". Nabi dengan tajam bertanya: "Maukah kau duduk di rumah ayah dan ibumu, lalu melihat apakah hadiah itu akan datang kepadamu?"
Di sini, korupsi tidak sekadar merugikan rakyat secara ekonomi atau negara secara hukum. Korupsi adalah pembangkangan teologis—ia merugikan agama. Hadiah yang diterima Ibn al-Lutbiyyah merobek prinsip keadilan zakat. Menggelapkan mantel kemudian dijual ke pedagang berarti meremehkan harta umat. Ia adalah noda yang menodai sakralitas kepemimpinan dan amanah
Maka korupsi dalam perspektif ini adalah bentuk keserakahan yang menolak percaya bahwa rezeki sudah diatur, sebuah "kekufuran kecil" dalam tindakan. Korupsi, dengan demikian, adalah upaya memprivatisasi yang publik. Ia mencuri hak Tuhan yang dititipkan pada kaum dhuafa. Ia menjadikan agama hanya sebagai jubah, sementara di baliknya, nafsu terus menggerogoti.
Namun, sejarah Islam juga tidak hitam-putih. Kaku dan hanya satu warna. Ada sebuah oase kebijaksanaan dalam keadilan yang presisi. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, saat ,Amul Maja’ah (tahun kelaparan) mencengkeram Madinah, kita menemukan sebuah paradoks hukum yang indah. Hatib bin Abi Balta’ah melaporkan budaknya yang mencuri dan menyembelih unta.
Secara legalistik, syarat nisab terpenuhi. Namun Umar, dengan ketajaman nurani, menolak menjatuhkan hukuman potong tangan. Umar melihat ada yang melampaui teks. Ia menemukan bahwa sang pencuri didorong oleh kelaparan yang eksistensial, bukan oleh keserakahan yang struktural. Di sini, mens rea atau niat jahat itu absen.
Sang pelaku, budak atau pegawai itu mencuri untuk menyambung nyawa, bukan untuk menumpuk harta. Dan, anehnya Umar justru menegur sang majikan yang tidak memberi upah layak.Di sinilah letak perbedaannya: Korupsi adalah kejahatan mereka yang "kenyang" namun ingin menelan lebih banyak, sementara pencurian karena lapar adalah jeritan mereka yang "hak"nya dirampas oleh sistem yang korup.
Selain itu ada fenomena yang ganjl. Sang Pengadil di meja hijau nampak amat ragu dengan pengambilan sanksi. Dari isitulah kemudian kita mengenal asas keadilan: bagi hakim, lebih baik memaafkan orang yang mungkin bersalah, daripada menghukum orang yang mungkin tak bersalah.
Korupsi tidak hanya merugikan rakyat secara materi, ia merusak estetika iman. Ia membuat doa-doa terasa hambar karena diucapkan oleh mulut yang memakan hak orang lain. Jika di zaman Nabi dan Umar keadilan diletakkan pada tempatnya—menindak tegas yang rakus dan melindungi yang terdesak— dengan kontek mantel (baju perang) milik umat dan unta milik "oligorki," --maka hari ini kita sering melihat yang sebaliknya: hukum yang tajam pada yang lapar, namun tumpul pada mereka yang bergelimang gratifikasi.
Bisa jadi tindakan korupsi adalah sebentuk ateisme praktis. Seseorang bisa saja bersujud ribuan kali, namun ketika ia mengambil yang bukan haknya, ia sedang berkata bahwa Tuhan tidak melihat, atau setidaknya, Tuhan bisa disuap dengan sekadar ritual. Dan di situlah, agama kehilangan jiwanya. Wallahu'alam bishawab.