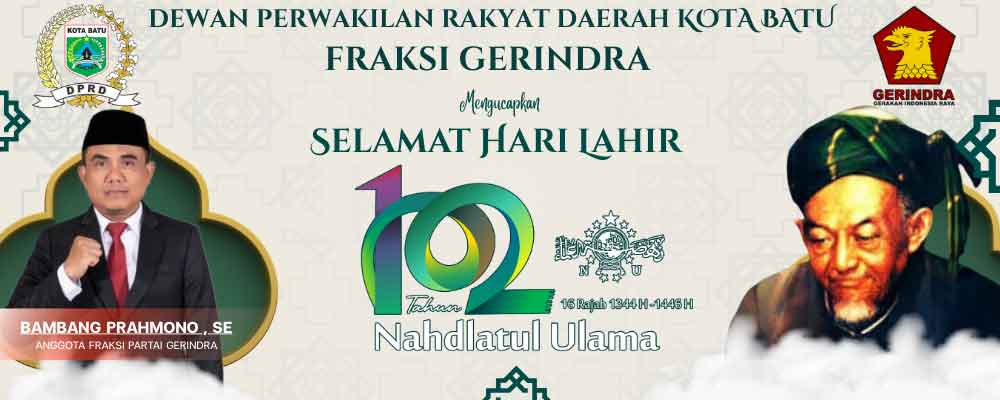Khariri Makmun. Foto: dok. priabadi
Khariri Makmun. Foto: dok. priabadi
Oleh : Khariri Makmun*
Tulisan ini kami sajikan untuk menjawab tuduhan naif tentang ketidaksesuaian Pendidikan Agama dengan kebutuhan Bangsa.
Ada anggapan yang belakangan cukup nyaring terdengar, bahwa pesantren dan lembaga pendidikan agama lainnya tak lagi relevan dengan kebutuhan zaman. Katanya, jurusan-jurusan agama seperti tafsir, hadis, syariah, fikih, akidah, atau akhlak tidak sejalan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) negara yang harus bersaing secara global dalam bidang teknologi, sains, dan ekonomi.
Maka, muncul logika serampangan yang menyimpulkan: jika pendidikan agama tak bisa melahirkan insinyur, ahli bioteknologi, atau ilmuwan roket, berarti ia tak layak diperjuangkan—bahkan sebaiknya ditutup.
Pandangan seperti ini bukan hanya keliru, tapi juga menunjukkan kedangkalan cara berpikir yang gagal memahami peran strategis pendidikan agama—terutama pesantren—dalam membangun watak bangsa.
Menganggap bahwa satu-satunya ukuran kemajuan bangsa adalah penguasaan sains dan teknologi semata, tanpa menyertakan integritas moral dan kearifan sosial, adalah kekeliruan fatal. Negara bukan sekadar mesin industri. Negara adalah organisme sosial dan budaya. Dan dalam konteks ini, pesantren memainkan peran krusial.
Pertama-tama, mari kita luruskan: siapa bilang pesantren hanya mengajarkan kitab kuning dan ilmu-ilmu klasik semata? Pesantren masa kini tidak statis. Ia dinamis. Ia bertransformasi. Banyak pesantren hari ini justru mengintegrasikan kurikulum agama dengan sains dan teknologi. Para santri bukan hanya belajar tafsir atau hadis, tapi juga fisika, matematika, komputer, pertanian, bahkan robotik. Pesantren tidak tertinggal. Mereka hanya punya prioritas yang berbeda: membangun karakter sebelum membangun karier.
Kedua, pendidikan agama—yang dianggap ‘tidak relevan’ itu—justru menjadi fondasi dari pendidikan karakter yang hari ini sangat dibutuhkan bangsa. Apa gunanya memiliki insinyur hebat kalau korup? Apa faedahnya punya ahli ekonomi kelas dunia kalau tak punya integritas moral dan gampang disuap? Inilah sumbangsih tak terlihat pesantren: mereka mendidik SDM yang bukan hanya cerdas, tapi juga berakhlak, punya etika sosial, dan tahan terhadap godaan kekuasaan.
Ketiga, kritik yang menyebut pesantren tidak menghasilkan SDM yang “dibutuhkan negara” sangat sempit dalam memaknai kebutuhan bangsa. Apa hanya ahli fisika dan kimia yang dibutuhkan bangsa ini? Bagaimana dengan SDM yang paham hukum waris, yang bisa menyelesaikan sengketa syariah, yang bisa jadi mediator konflik sosial, yang bisa menjadi pemimpin moral masyarakat? Atau lebih sederhana: siapa yang akan menjadi imam salat, penceramah keagamaan, guru ngaji anak-anak? Ataukah bangsa ini ingin tumbuh menjadi entitas sekuler yang tercerabut dari akar nilai dan spiritualitas?
Keempat, pesantren bukan lembaga nostalgia. Ia adalah laboratorium sosial yang aktif. Di sana karakter SDM bangsa ditempa dengan kedisiplinan, keikhlasan, kesederhanaan, dan jiwa gotong royong. Anak-anak pesantren bangun sebelum fajar, belajar tanpa banyak fasilitas, mandiri dalam mengatur hidup. Mereka ditempa dalam kultur egaliter dan spiritual yang kuat. Bandingkan dengan sebagian sekolah umum yang terlalu kering dari aspek moral dan terlalu kaku dalam relasi guru-murid.
Kelima, siapa bilang pesantren anti terhadap sains? Sejak dulu para ulama pesantren belajar ilmu hisab (astronomi), ilmu mantik (logika), ilmu falaq, hingga ilmu kesehatan berbasis Islam. Bahkan dalam sejarahnya, pesantren melahirkan banyak tokoh pembaharu yang justru menggerakkan pendidikan modern. Lihat saja sosok Hasyim Asy’ari, Ahmad Dahlan, atau Mahmud Yunus—semuanya berakar dari tradisi pesantren, tapi punya orientasi pembaruan pendidikan yang kuat.
Keenam, keunggulan pesantren yang jarang disorot adalah penguasaan bahasa asing. Santri-santri bisa membaca literatur Arab klasik yang sangat kaya, bahkan menguasai bahasa Inggris sebagai bekal komunikasi global. Mereka tidak kalah bersaing. Banyak alumni pesantren yang diterima di universitas top dunia, dari Al-Azhar hingga Harvard, dari Madinah hingga Melbourne. Jadi tuduhan bahwa pesantren tidak melahirkan SDM berkualitas hanyalah klaim kosong yang tidak berbasis data.
Ketujuh, faktanya, banyak pesantren sudah mengembangkan pendidikan vokasional. Mereka punya program keterampilan seperti pertanian, peternakan, perbengkelan, multimedia, hingga bisnis digital. Santri tidak hanya jadi ustaz, tapi juga teknopreneur, desainer, hingga pengelola start-up berbasis nilai. Jadi, jangan sempitkan makna pesantren hanya sebagai tempat tafsir dan fikih, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dan kontributif.
Kedelapan, negara ini sedang menghadapi krisis nilai. Korupsi merajalela. Radikalisme tumbuh subur. Polarisasi sosial makin tajam. Di tengah krisis ini, pesantren tampil sebagai benteng moral. Ia mengajarkan moderasi beragama, nasionalisme religius, dan cinta tanah air. Ia melahirkan kader-kader pemimpin yang tidak hanya pintar, tapi juga punya orientasi etis. Bandingkan dengan beberapa institusi pendidikan yang justru mencetak orang pintar tapi rakus, cerdas tapi manipulatif.
Kesembilan, keberhasilan pesantren dalam mencetak SDM unggul bisa dilihat dari jejak alumni mereka di berbagai sektor. Banyak santri menjadi menteri, diplomat, rektor, penulis, aktivis, pengusaha, bahkan ilmuwan. Lihat jajaran tokoh nasional seperti KH. Abdurrahman Wahid, KH. Ma’ruf Amin, KH. Hasyim Muzadi semuanya berlatar pesantren. Bahkan sejumlah bupati, gubernur, hingga pejabat tinggi negara berakar dari pesantren. Apakah mereka tidak relevan?
Kesepuluh, negara yang besar bukan hanya negara yang teknologinya maju. Tapi negara yang punya ruh, punya jiwa, punya akar budaya. Pendidikan agama—termasuk pesantren—adalah penopang utama dalam membangun ruh kebangsaan itu. Ketika Jepang bangkit pasca-Perang Dunia II, bukan teknologi yang lebih dulu dibangun, tapi pendidikan karakter. Ketika Amerika menghadapi krisis sosial, mereka kembali pada pendidikan etika. Jadi, argumen bahwa pendidikan agama tidak punya kontribusi dalam pembangunan adalah ahistoris.
Kesebelas, pesantren juga memainkan peran penting dalam pembangunan desa dan kawasan pinggiran. Banyak pesantren menjadi pusat pemberdayaan ekonomi, pusat pelayanan kesehatan, bahkan pusat mitigasi bencana. Mereka terhubung langsung dengan masyarakat bawah dan memahami kebutuhan riil rakyat. Sementara banyak kampus elite justru sibuk berteori dan jauh dari praktik sosial.
Keduabelas, kritik terhadap pesantren juga gagal membaca konteks geopolitik dan identitas kebangsaan Indonesia. Bangsa ini tidak dibangun dengan semata-mata akal rasionalistik Barat. Indonesia tumbuh dari perpaduan antara spiritualitas Timur dan rasionalitas modern. Dan pesantren adalah simpul penting dari integrasi ini. Menyingkirkan pesantren dari sistem pendidikan nasional, sama dengan mencabut akar kultural bangsa ini.
Ketigabelas, pendidikan agama bukan sekadar pengajaran dogma. Ia adalah pengajaran nilai. Di tengah zaman di mana manusia gampang menjadi zombie digital, terasing dari nilai-nilai luhur, maka pesantren tetap menawarkan oase: ajaran hidup bermakna, relasi yang hangat, hidup sederhana tapi bernilai. Ini adalah keunggulan yang tidak bisa direplikasi oleh sistem pendidikan berbasis algoritma dan gawai semata.
Keempatbelas, jika SDM unggul adalah SDM yang bisa berpikir kritis, punya empati sosial, mampu hidup dalam komunitas, tahan banting, dan punya visi hidup, maka pesantren adalah tempat yang tepat. Santri hidup dalam komunitas heterogen, belajar memimpin dalam kelompok, mengelola konflik, mematuhi aturan, dan tetap produktif dalam kondisi sederhana. Ini adalah kompetensi sosial yang langka dan sangat dibutuhkan dunia kerja modern.
Kelima belas, anggapan bahwa jurusan-jurusan seperti tafsir dan hadis tidak relevan, menunjukkan ketidaktahuan akan pentingnya ilmu-ilmu itu. Tafsir dan hadis adalah ilmu hermeneutika tingkat tinggi yang menuntut logika tajam, bahasa yang kuat, dan kemampuan kritik teks. Para ahli tafsir bukan orang sembarangan. Mereka punya kemampuan berpikir sistemik dan metodologis yang bisa diaplikasikan di berbagai bidang. Bahkan kemampuan ini bisa diterjemahkan ke dalam bidang riset, kebijakan publik, hingga analisa sosial.
Keenam belas, banyak pesantren juga menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga riset, perguruan tinggi, NGO, bahkan lembaga internasional. Mereka tidak anti terhadap modernitas. Mereka hanya menempatkan agama sebagai orientasi moral, bukan sebagai penghambat kemajuan. Justru dengan basis nilai ini, kemajuan yang dicapai akan lebih manusiawi dan berkelanjutan.
Ketujuh belas, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada teknokrat. Negara ini butuh negarawan, ulama, guru bangsa. Dan semua itu tumbuh dari ekosistem yang memberi ruang kontemplasi, nilai, dan kedalaman spiritual. Pesantren adalah inkubator dari sosok-sosok seperti ini. Mencabut pesantren dari sistem pendidikan sama saja dengan membunuh masa depan kepemimpinan moral bangsa.
Kedelapan belas, dalam era disrupsi informasi, pesantren juga mulai memanfaatkan teknologi untuk dakwah, pembelajaran daring, dan transformasi digital lainnya. Banyak santri kini mahir membuat konten edukatif, menulis opini kritis, mengembangkan aplikasi islami. Mereka adaptif dan tidak gagap teknologi. Mereka hanya punya cara pandang yang tidak menuhankan teknologi.
Kesembilan belas, argumen yang mengatakan bahwa pendidikan agama dan pesantren tidak dibutuhkan SDM negara hanyalah ilusi dari mentalitas yang terlalu memuja sains tapi miskin nilai. Yang dibutuhkan bangsa ini bukan hanya otak encer, tapi juga hati yang lapang. Bukan hanya kecanggihan, tapi juga kearifan. Dan semua itu, bisa tumbuh dari pesantren.
Kesimpulannya, tuduhan bahwa pesantren tidak relevan hanyalah bias modernisme sekuler yang gagal membaca kekayaan sistem pendidikan bangsa ini. Pesantren bukan musuh kemajuan. Ia adalah pondasi bangsa. Ia bukan beban negara. Ia adalah modal sosial dan spiritual yang tak ternilai. Maka, tugas kita bukan melemahkan pesantren, apalagi menghapus pendidikan agama, tapi justru memperkuat, memodernisasi, dan mengintegrasikannya ke dalam sistem pembangunan nasional.
*Penulis adalah Pengasuh Pesantren Algebra, Ciaiwi, Bogor.