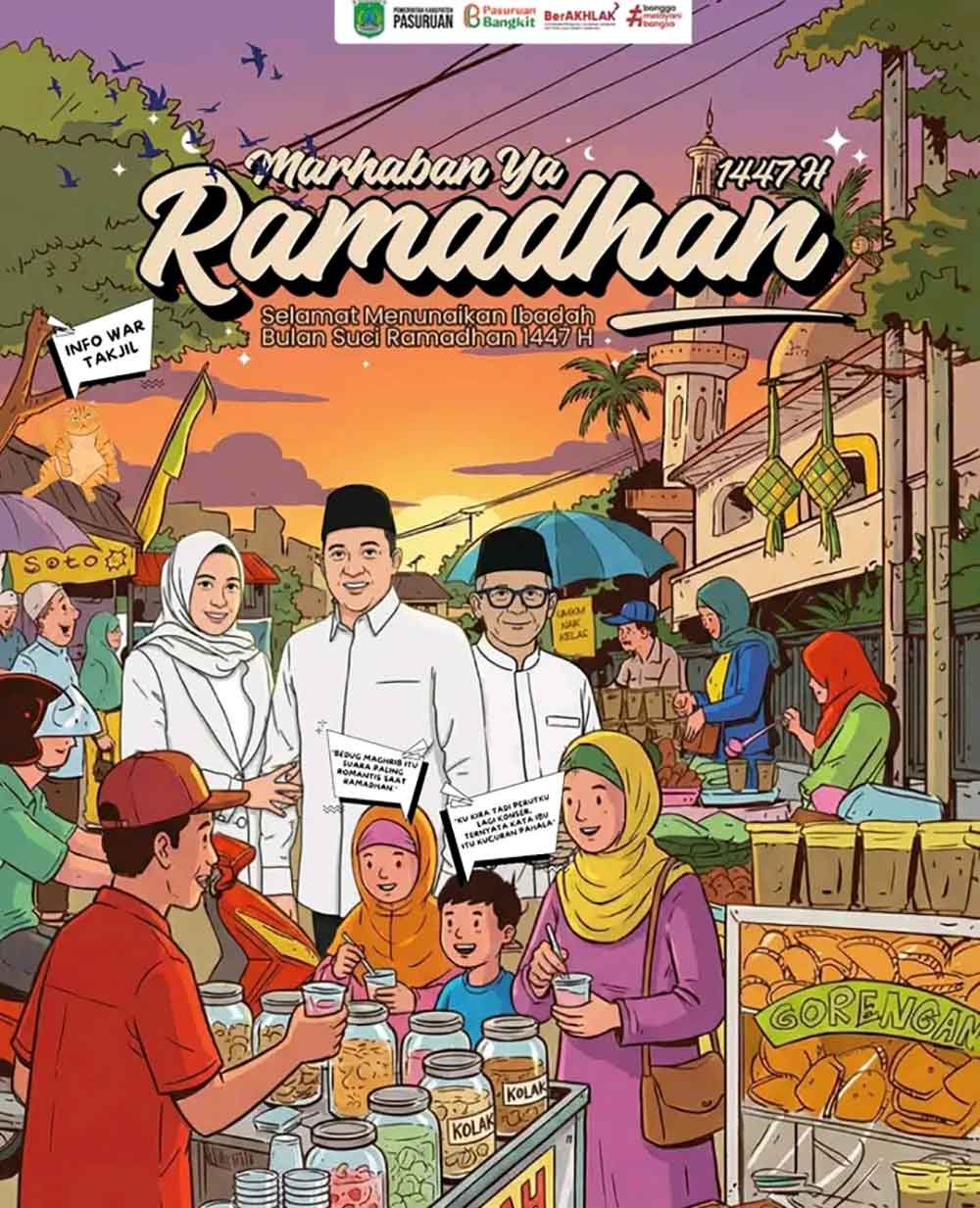Foto: Instagram Aguk Irawan MN.
Foto: Instagram Aguk Irawan MN.
Oleh: Aguk Irawan MN
Barangkali, ada semacam ironi dalam usaha "menghidupkan" pemikiran dan warisan Gus Dur. Ironi yang bukan lahir dari ketidakmampuan, melainkan dari pilihan sadar untuk memisahkan raga dari ruh. Ketika sebuah buku, "Menghidupkan Gus Dur", karya Gus Yahya Cholil Staquf dipublish menjelang Muktamar 34 di Lampung dan hadir di ruang publik.
Buku ini dengan sangat meyakinkan telah menjanjikan kesinambungan narasi, sebuah jembatan yang menghubungkan kearifan masa lalu dengan tantangan kekinian. Namun, janji itu dalam perjalanannya terasa hambar, bahkan mungkin berbalik arah dengan substansi perlawanan yang pernah ditanamkan oleh almarhum KH. Abdurrahman Wahid.
Gus Dur, dalam ingatan kolektif kita, adalah anomali yang indah: seorang ulama yang tak lelah membela minoritas, seorang presiden yang memilih dipecat ketimbang berkompromi dengan pelaku politik kotor, dan seorang pemikir yang meletakkan kemanusiaan di atas segala dogma. Salah satu jejaknya yang mungkin tersembunyi dari sorot kamera, namun nyata dalam sikap politiknya, adalah kepekaannya terhadap isu lingkungan.
Gus Dur, dengan segala keluwesan pemikirannya, cenderung menempatkan hak asasi manusia dan keberlanjutan hidup di pusat kebijakan. Referensi tentang sikapnya yang tidak pro-tambang mungkin tidak termaktub dalam satu dekrit presiden, melainkan tertebar dalam sikapnya yang menolak pembangunan yang merugikan rakyat kecil dan lingkungan. Ia menolak pendekatan pembangunan yang eksploitatif, yang sering kali menjadi watak industri pertambangan.
Gus Dur, dalam rekam jejaknya sebagai presiden, dikenal konsisten menolak industri ekstraktif yang merusak lingkungan. Ia adalah satu-satunya Presiden Indonesia yang tidak pernah memberikan konsesi tambang. Sikap ini bukan tanpa alasan, melainkan berakar dari kesadaran mendalam akan keadilan ekologis dan keberlanjutan hidup masyarakat adat dan lokal.
"Rekam jejak Gus Dur menunjukkan konsistensinya menolak industri ekstraktif yang merusak sumber daya alam," ungkap jaringan Gusdurian, menegaskan warisan sikap sang tokoh. Inayah Wahid, putri Gus Dur, bahkan menggugat Peraturan Pemerintah (PP) yang memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan, menunjukkan betapa sikap ini dipegang teguh oleh keluarga dan pengikut setianya.
Di sinilah letak perbedaan mencolok dengan penerusnya, Gus Yahya Cholil Staquf. Di bawah kepemimpinan Gus Yahya di PBNU, organisasi tersebut kini secara eksplisit terlibat dalam pengelolaan konsesi tambang, sebuah langkah yang memicu konflik internal dan kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Mahfud MD dan elite PBNU lainnya. PBNU di bawah Gus Yahya menerima tawaran pemerintah untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).
Perbedaan ini bukan sekadar soal teknis kebijakan, melainkan soal etos. Gus Dur mengajarkan politik etis, di mana kekuasaan dan sumber daya alam adalah amanah yang harus digunakan untuk kesejahteraan umat, bukan untuk memperkaya segelintir elite atau organisasi. Sikap Gus Yahya yang pro-tambang, meskipun diklaim demi kemaslahatan umat, secara diametral bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi dan keadilan ekologis yang secara implisit diyakini oleh Gus Dur.
Ironi lain adalah gagasan "Fiqih Peradaban" yang pernah santer mengemuka. Fiqih Peradaban, yang digagas Gus Yahya, dimaksudkan sebagai upaya pelembagaan nilai-nilai luhur Islam untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil dan damai. Sebuah ikhtiar mulia. Namun, ketika gagasan luhur ini berbenturan dengan realitas ekonomi yang mengedepankan eksploitasi sumber daya alam, narasinya menjadi pincang. Bagaimana mungkin membangun "peradaban" di atas lahan yang dieksploitasi, mengabaikan prinsip-prinsip keadilan lingkungan yang secara implisit diajarkan Gus Dur melalui tindakannya?
Gus Dur berpolitik dengan kelincahan manuver personal, mengedepankan etika dan kemanusiaan di atas segalanya. Gus Yahya sebaliknya, mencoba membangun "mesin peradaban" yang kokoh melalui birokrasi organisasi. Perbedaannya terletak pada substansi: Gus Dur fokus pada nilai kemanusiaan universal, sementara langkah Gus Yahya membawa gerbong nahdliyin saat ini seakan terjebak dalam pragmatisme ekonomi yang menafikkan warisan etis tersebut.
Sebab, keputusan menerima tambang, bagi banyak pihak, adalah bentuk pengkhianatan terhadap khittah moral Gus Dur, menjadikan klaim "menghidupkan Gus Dur" terdengar seperti sekadar retorika yang berjarak dari tindakan nyata. Gus Dur adalah budayawan dan humanis yang menolak komersialisasi sumber daya alam secara membabi buta; langkah PBNU saat ini, dengan segala bantalannya, tampak berjalan di arah yang berlawanan.
Mungkin saja buku "Menghidupkan Gus Dur" telah berhasil secara naratif, tetapi realitas politik Gus Yahya, terutama terkait isu tambang, menjadi antitesis dari apa yang ia coba hidupkan. Gus Dur adalah tentang perlawanan terhadap ketidakadilan struktural; Gus Yahya, dalam isu ini, seolah menjadi bagian dari struktur itu sendiri. Inilah tragedi dari sebuah warisan: dihidupkan namanya, tapi dilupakan ruh perjuangannya. Wallahu'alam bishawab.