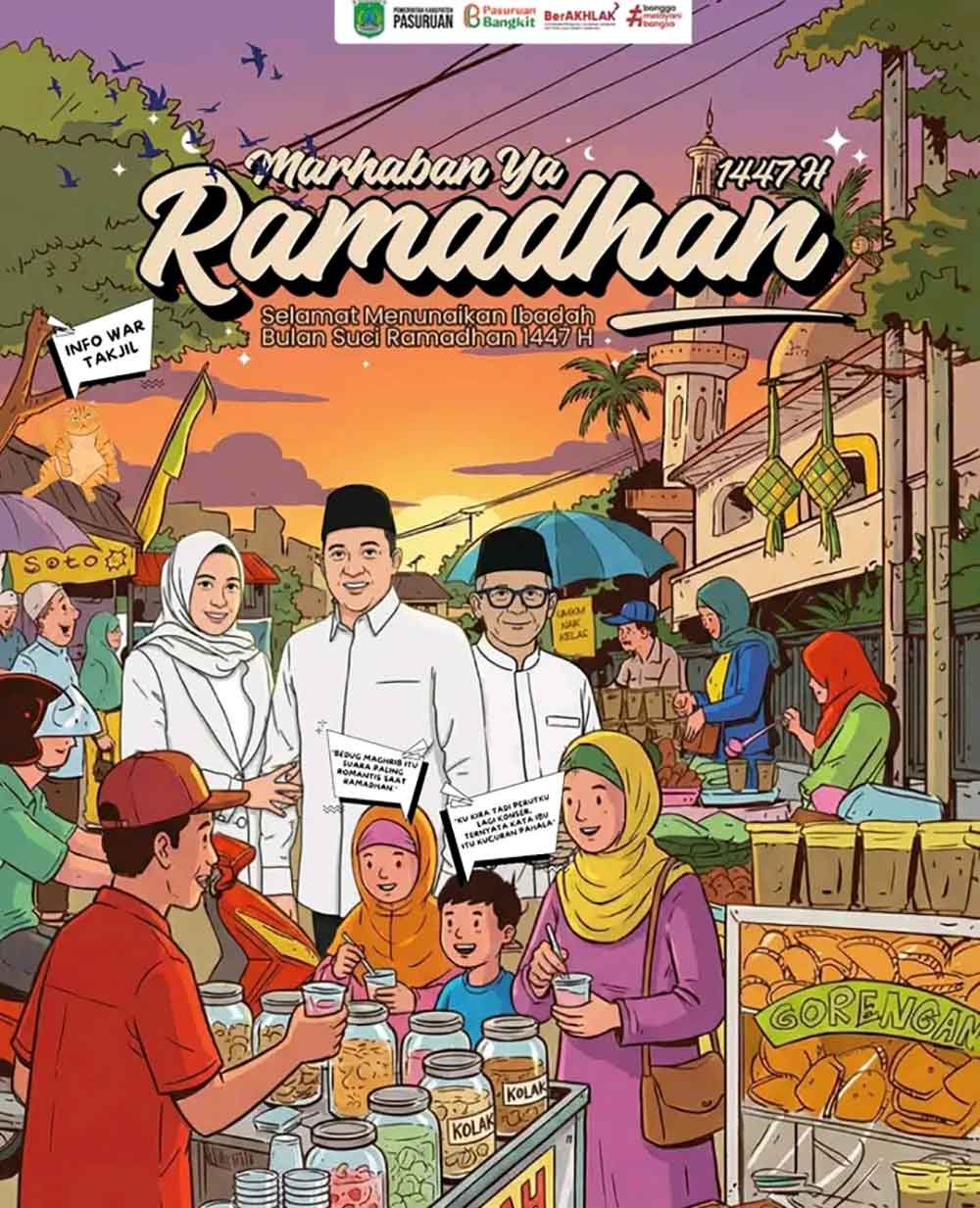Aguk Irawan MN. Foto: istimewa
Aguk Irawan MN. Foto: istimewa
Oleh: Aguk Irawan MN
Sebenarnya ini bukan soal nahdliyin, atau jamaah an-nahdliyah, tapi ini murni soal elit PBNU, tetapi tentu saja ini dampaknya bisa ke semua wajah nahdliyin. Ada yang menyebutnya "angin ribut" dalam cangkir teh. Klise, barangkali. Tapi, ketika angin ribut itu berpusar di jantung Pengurus Besar, ia bukan sekadar metafora. Ia adalah pertarungan makna, wewenang, dan mungkin, sedikit soal ego, yang berkelindan dalam struktur organisasi paling berpengaruh di negeri ini.
Kabar yang beredar bak risalah kilat: Rapat Harian Syuriah PBNU, yang dipimpin langsung oleh Rais Aam, telah memutuskan agar K.H. Yahya Cholil Staquf—Gus Yahya, Ketua Umum Tanfidziyah—mengundurkan diri dalam tempo tiga hari. Alasannya bermacam-macam, dari soal tata kelola keuangan yang dinilai bermasalah hingga isu kebijakan struktural yang dianggap memicu kegaduhan, termasuk polemik narasumber di sebuah universitas yang dikaitkan dengan Israel.
Tentu, ini bukan kali pertama NU diguncang dinamika internal. Sejak era Muktamar Situbondo hingga polemik "NU struktural" versus "NU kultural", organisasi ini selalu hidup dalam dialektika. Di sinilah kita teringat pada sosok K.H. Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Sang maestro paradox. Bagaimana ia menyikapi "gejolak" semacam ini? Barangkali dengan tawa renyah, atau mungkin kalimat pendek yang menusuk: "Gitu aja kok repot!"
Gus Dur pernah berkata, "NU ini bukan organisasi politik, tapi organisasi keagamaan. Khidmah kita adalah untuk umat, bukan untuk kekuasaan." Meskipun sering kali dianggap mendobrak tradisi, Gus Dur sangat menghormati mekanisme organisasi dan, yang terpenting, peran para kiai Syuriah. Ia tahu betul kapan harus berhenti, demi menjaga keutuhan dan martabat jam'iyyah.
Jika kita merenungkan "langkah bijaksana" ala Gus Dur, mungkin ia akan menertawakan keruwetan ini dengan tawa khasnya, lalu mengingatkan para pihak akan esensi ukhuwah nahdliyah (persaudaraan nahdliyah). Persoalan internal sebesar apa pun, ujarnya, harus diselesaikan di meja musyawarah dengan kepala dingin dan hati lapang, bukan dengan saling melempar risalah ke media atau mengumpulkan massa.
Bagi Gus Dur, organisasi sebesar NU adalah rumah bersama, bukan semata soal kekuasaan. Dinamika dan ger-geran adalah bagian dari denyut nadi demokrasi khas pesantren, yang mengutamakan musyawarah mufakat di atas segalanya. Ia selalu menekankan pentingnya peran Syuriah sebagai majelis tertinggi yang menjaga ruh keagamaan dan marwah organisasi, sementara Tanfidziyah menjalankan roda harian. Dalam pandangan Gus Dur, keduanya harus berjalan seimbang, dengan kearifan (hikmah) sebagai kompas utama.
Tapi, risalah yang beredar itu terkesan tegang, nyaris ultimatum. Ia seperti keputusan palu godam, terasa bukan bisikan lembut kearifan. Dan, sudah bisa ditebak Gus Yahya dengan gayanya yang khas, sepertinya akan sulit mundur, sebab menyebut keputusan itu sepihak dan tidak melalui klarifikasi terbuka. Di sinilah letak ironinya. NU, yang mengajarkan tawasut (moderat) dan tasamuh (toleran), kini diuji dengan cara penyelesaian masalah yang terkesan buru-buru.
Padahal sering kita mendengar adagium klasik NU: "Mempertahankan nilai-nilai lama yang baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik" (al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah). Nilai lama yang baik adalah penghormatan terhadap hierarki, di mana Rais Aam adalah pucuk pimpinan spiritual. Nilai baru yang lebih baik mungkin adalah transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi modern, yang juga harus diakomodasi tanpa menggerus marwah ulama.
Langkah bijaksana ala Gus Dur dalam situasi ini mungkin akan melibatkan beberapa hal:
Kembali ke Khittah: Menempatkan AD/ART sebagai pijakan, namun dengan kelenturan akhlakul karimah. Peran Syuriah sebagai otoritas tertinggi harus dihormati, namun Tanfidziyah juga berhak atas proses yang adil.
Dialog Tertutup, Hasil Terbuka: Konflik internal sebaiknya diselesaikan di ruang bahtsul masail internal, dengan Rais Aam sebagai penengah yang adil, bukan melalui "risalah bocor" yang memicu spekulasi publik.
Mungkin juga langkah bijaksana yang lain, sekali lagi, memberikan kesempatan yang adil bagi Ketua Umum Tanfidziyah untuk memberikan klarifikasi. Kemudian dengan kesatria dan bijaksana ia akan memilih mundur, sebab bagaimanapun ultimatum sudah dijatuhkan. Perlawanan atau pembangkangan, bisa merusak martabat masayikh dan tentu saja, demi keberlangsungan khidmah NU bagi negeri ini yang lebih kondusif, menyongsong satu abad, sementara konflik terbuka hanya akan melemahkan NU di mata umat dan bangsa. NU terlalu besar dan penting untuk sekadar menjadi panggung perebutan pengaruh.
Kita bisa belajar dari kutipan bijak para pendahulu. Hadratusyaikh K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri NU, yang berpesan agar menjaga persatuan umat lebih utama ketimbang memenangkan satu faksi. Atau pandangan intelektual Muslim kenamaan, Nurcholish Madjid (Cak Nur), yang sering mengingatkan bahwa substansi gerakan Islam adalah kemaslahatan, bukan perebutan jabatan semata.
Namun dalam peristiwa genting, sering muncul "tokoh" pahlawan kesiangan, yaitu ketika kondisi sedikit runyam, pahlawan itu datang, ia adalah Sekjen PBNU (Gus Ipul) yang menghimbau seluruh warga NU diharap tenang dan menjaga keteduhan. Fokus PBNU seharusnya pada persoalan umat yang lebih besar, bukan drama internal. Padahal hampir seluruh nahdliyin paham alurnya, rasanya sangat sulit diterima bahwa Sekjen tidak ada dalam sengkarut ini, bahkan mungkin dia lebih paham darimana awal badai ini berhembus?
Permintaan mundur Gus Yahya oleh Syuriah adalah episode baru dalam sejarah panjang dinamika NU. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi soal bagaimana para kiai dan intelektual NU, dalam warisan tradisi Gus Dur, menemukan kembali jalan hikmah di tengah "angin ribut" kekuasaan. Sebab, pada akhirnya, yang "abadi" dari NU adalah perjuangan kiai, santri, dan umatnya untuk menjaga tradisi, bukan jabatan elit sebagai Pengurus Besar. Wallahu'alm bishawab.