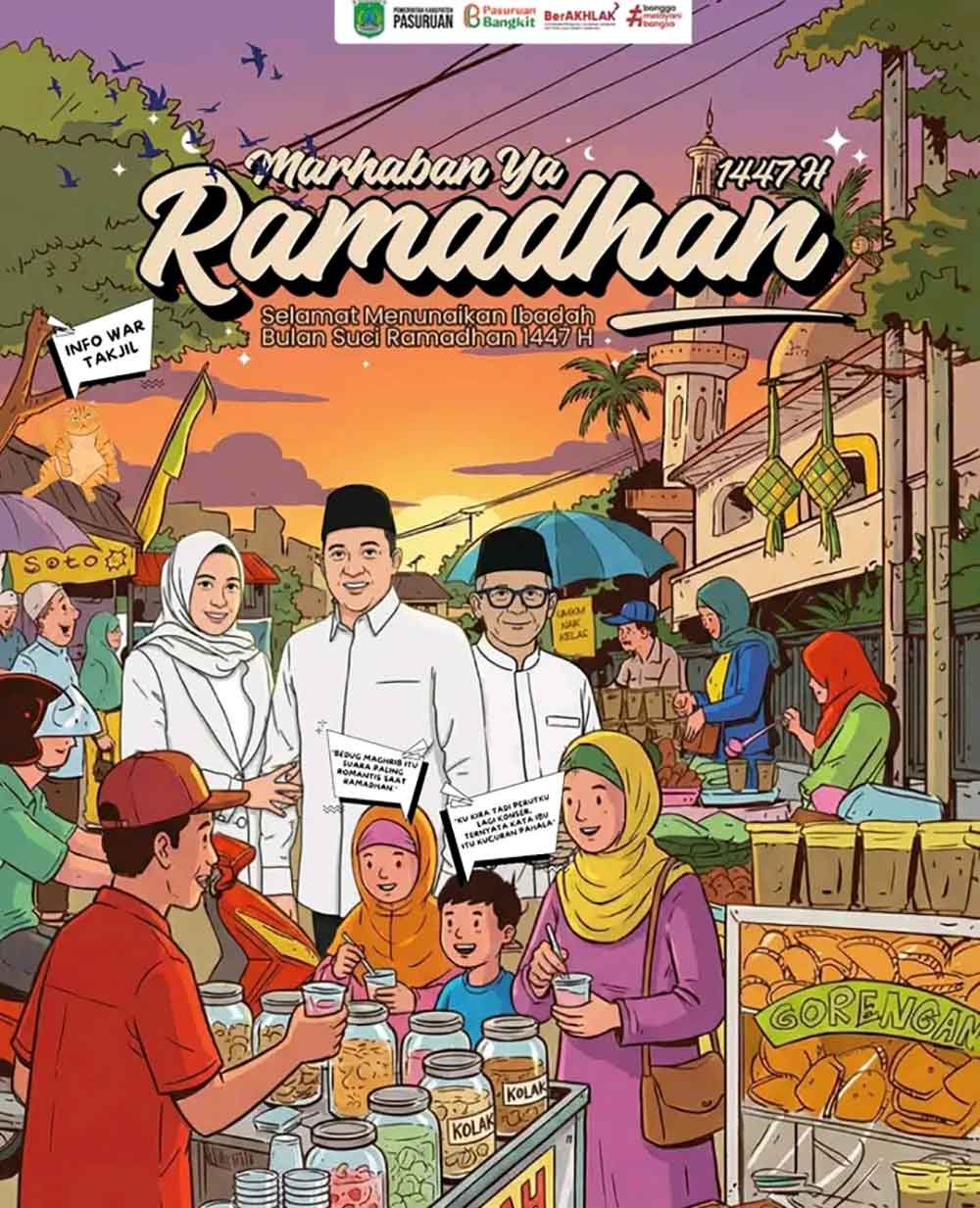Oleh: Dr. KHA Musta'in Syafi'ie MAg. . .
Wa’alaa alladziina haaduu harramnaa maa qashashnaa ‘alayka min qablu wamaa zhalamnaahum walaakin kaanuu anfusahum yazhlimuuna (118). Tsumma inna rabbaka lilladziina ‘amiluu alssuu-a bijahaalatin tsumma taabuu min ba’di dzaalika wa-ashlahuu inna rabbaka min ba’dihaa laghafuurun rahiimun (119).
Ayat 118 menunjuk, bahwa seorang muslim tidak boleh mengharamkan atas diri sendiri sesuatu yang pada dasarnya halal. Jika hal itu diback-up dengan sumpah, semisal: “wallahi, saya tidak akan makan ikan bandeng”, maka wajib dipatuhi. Jika makan, apapun alasannya, maka dia melanggar sumpah. Sumpah begini ini merepotkan dan sebaiknya didibatalkan dengan cara membayar kafarat.
Bagi mereka yang melakukan hal di atas karena tidak mengerti (bi jahalah), lalu bertobat dan memperbaiki diri (tsumma tabu min bad' dzalik wa ashlahu), maka Tuhan mengampuni. Begitulah ayat studi 119 bertutur.
Persoalan membias pada pengharaman barang halal terkait dengan strategi dakwah atau balas jasa. Bolehkah?
Pertama, untuk balas jasa, katanya, Kiai Khalil Bangkalan pernah mendapatkan musibah di laut, lalu ada seekor ikan yang baik hati dan menolong. Kiai ditopang di atas punggung ikan, lalu dibawa minggir ke tepi pantai dan selamatlah beliau. Sebagai balas jasa, di hadapan ikan itu beliau bersumpah: "mulai sekarang, aku haramkan diriku dan keturunanku mengkonsumsi kamu dan keturunanmu".
Lepas dari kisah ini benar dan tidak, maka jadilah hukum haram tersebut mengikat atas diri kiai Khalil. Persoalannya, apakah hukum tersebut juga berlaku bagi keturunan kiai Khalil? Perspektif dhahir tidak. Karena pada dasarnya, seseorang tidak bisa dibebani tanggung jawab hukum dari orang lain. Kecuali pada persoalan yang sudah ditentukan oleh Nash secara tegas, seperti diyat 'aqilah. Yakni denda pembunuhan yang dibebankan secara gotong-royong pada keluarga, bukan pada diri si pembunuh.
Lazimnya, semisal tragedi kiai Khalil itu dikisahkan pada keluarga, lalu diwasiatkan, sehingga menjadi pugeran keluarga yang dipatuhi secara turun-temurun. Meskipun keluarga tersebut tidak terbebani efek sumpah, biasanya mereka patuh. Andai saja ada yang melanggar, -meski tiak dosa- biasanya ada efek buruk menimpa dirinya. Semisal gatal-gatal atau sakit aneh.
Cara penyembuhannya -biasanya- sulit lewat medik, melainkan lewat magic. Semisal bersedekah, istighfar, mengkhatamkan al-qur'an di kuburan leluhur yang menjatuhkan sumpah dulu sembari meminta maaf dan lain-lain. Atau menurut nasehat kiai ahli.
Begitu halnya dengan pelarangan sesuatu yang aslinya halal sebagai bagian dari strategi dakwah, semisal toleransi pada pemeluk agama lain. Katanya, kanjeng Sunan Kudus melarang warga Kudus yang beragama Islam makan daging sapi. Hal demikian atas pertimbangan toleransi pada pemeluk agama Hindu yang tidak mengkonsumsi daging sapi. Bagi Hindu, sapi adalah hewan sakral yang dimuliakan.
Ini cara berdakwah yang brilian, bijak dan bermaslahah. Sunan Kudus sangat paham bahwa Islam kini sedang berada di bumi nusantara yang beragam dan majemuk. Tapi juga sangat mengerti bahwa keimanan adalah melebihi segala-galanya.
Itulah, makanya beliau berdakwah dengan cara menahan diri tidak mengkonsumsi daging sapi di tengah-tengah masyaramat yang sedang menghormati sapi. Hal itu bukan karena haramnya daging sapi dalam syari'ah Islam, melainkan sebatas tepo seliro, menjaga perasaan sesama. Lebih dari itu, toleransi ini sama sekali tidak merugikan Islam dan umat Islam serta tidak pula menguntungkan nonmuslim, tidak pula memberi peluang bagi mereka leluasa menguasai umat Islam.
Di sini nampak jelas, betapa kanjeng Sunan arif dalam mengkomparasikan efek maslahah dan mafsadah dalam berdakwah. Meski pelarangan mengonsumsi daging sapi tersebut tidak lazim dalam syariah Islam, tapi tidak berefek apa-apa bagi agama, justru menebar simpati kepda pemeluk agama lain.
Tidak hanya itu, kanjeng Sunan juga mendesain menara masjid Kudus dengan menggabungkan arsitek gaya arab, Jawa dan Hindu. Ada kubah dan ada pola kuil yang mencolok. Hingga kini nuansa Hindu pada menara itu masih tersaksikan. Sekali lagi, hanya sebatas karya seni belaka yang sama sekali tidak berefek apa-apa dan tidak merugikan apa-apa bagi umat Islam. Justru maslahahnya nyata-nyata ada.
Toleransi kanjeng Sunan Kudus ini senada dengan falsafah wong mancing ikan. Cost umpan yang dilempar ke perairan lebih sedikit dibanding dengan ikan buruan yang didapat. Inilah kecerdasan terpuji dari ijtihad kanjeng Sunan dalam menerapkan teori muqaranah (komparasi) berbasis ashlahiyah.
Sungguh tidak sama dengan masalah pemilihan kepala daerah, di mana calonnya ada yang nonmuslim, sementara ada calon yang muslim dan sama-sama punya plus-minus dalam kepemimpinan. Untuk persoalan ini, Tuhan sendiri turun tangan dengan menurunkan ayat-ayat suci yang pesannya tegas-tegas melarang seorang muslim memilih pemimpin nonmuslim.
Tidak sekadar melarang, Tuhan juga menunjukkan kebusukan-kebusukan mereka. Tidak saja Tuhan yang turun tangan, Rasulullah SAW juga mempertegas dengan tindakan nyata dalam sunnah fi'liyah. Lalu dikuatkan dengan praktik para sahabat, tabi'in hingga ulama' Nusantara ini tempo dulu.
Karena sangat besar risikonya dan sangat tinggi cost-nya bagi umat islam, makanya Rasulullah SAW, al-khulafa' al-rasyidun, para sahabat, para tabi'in, para imam madzhab, bahkan para wali songo tidak melakukan toleransi macam yang berpotensi merugikan umat islam. Itu bukan toleransi, melainkan bunuh diri.
Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad melawan penjajah bukan tidak mengerti ukhuwwah wathaniyah, bukan tidak faham ukhuwah basyariyah, melainkan karena berukhuwah, bertoleransi pada kontek ini sangat tidak tepat. Mereka adalah nonmuslim yang merusak dan merendahkan martabat bangsa yang mayoritas muslim, makanya, wajib diperangi.
Resolusi jihad kiai Hasyim itu merupakan realisasi dari iradah Allah SWT, di mana Dia tidak sudi memberi peluang kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang beriman. "wa lan yaj'al Allah li al-kafirin 'ala al-mu'minin sabila" (al-Nisa':141). Itulah sebabnya, maka sangat janggal jika ada fatwa, dalil agama yang membolehkan umat Islam memilih pemimpin kafir dalam kondisi normal, di mana pemimpin muslim ada dan mumpuni.
Kawan-kawan Ansor NU sekarang telah tega membuat bahtsul masail tandingan yang menentang keputusan bahtsul masa'il produk Syuriah yang mengharamkan memilih pemimpin nonmuslim. Ansor membolehkan dan publik sudah paham, bahwa Bahsul masail Ansor itu pesanan politik. Ini tragedi memprihatinkan sekaligus memalukan dalam sejarah NU, di mana fatwa kiai-kiai Syuriah dilawan oleh banomnya sendiri. Mudah-mudahan kawan-kawan Ansor segera sadar, bahwa sejatinya mereka berhasil memecah-belah kita, antara sesepuh NU dengan anak mudanya.
Andai ada Nash yang dipaksakan menjadi dalil bolehnya muslim memilih pemimpin nonmuslim, maka apakah harus disajikan utuh begitu saja tanpa pakai kearifan kedua?
Semisal, apa itu perlu disajikan kepada nonmuslim sebagai dalil penguat? Apa pula maslahahnya bagi agama dan bagi umat islam? Yang berpikiran jauh begini ini sirna dalam pikiran Ansor sekarang.
Ibarat aneka makanan yang disajikan di meja, maka orang pintar akan memilih makanan mana yang paling baik, paling bermaslahah bagi kesehatan diri. Bukan asal halal, bukan asal enak, lalu disantap. Apalagi jika makanan yang tersaji tersebut buruk-buruk dan tidak ada yang baik, maka wong pinter akan memilih tidak mengkonsumsi.
Di meja makan inilah keimanan pemuda Ansor diuji, tergoda menyantap atau menahan diri. Semoga Tuhan memberi hidayah dan segera meluruskan langkah kawan-kawan Ansor sehingga benar-benar menjadi Ansorullah, pembela Allah dan bukan pembela musuh Allah.